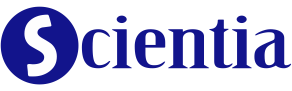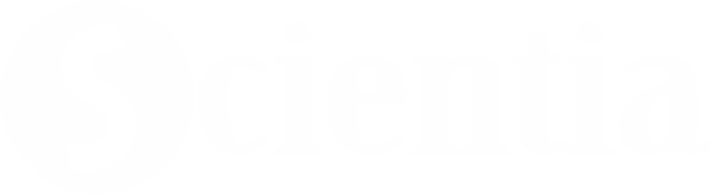Oleh: Hilda Septriani
(Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran, Bandung)
Istilah BIPA saat ini sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan, terutama dalam pengajaran bahasa. BIPA yang merupakan singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing menjadi salah satu program yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek (saat ini Kemendikti Saintek) untuk mengenalkan dan menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Tentunya hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yaitu “Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan”.
Untuk mendukung tujuan strategi diplomasi lunak melalui pengajaran BIPA bagi orang asing di berbagai penjuru dunia ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Bahasa dan Pusat Penguatan Pemberdayaan Bahasa (Pustanda) sudah bekerja sama dengan lebih dari 56 negara melalui 300 lembaga lebih yang terdiri dari sekolah, universitas, KBRI, KJRI, dan instansi bahasa lainnya. Merujuk pada laman https://bipa.kemdikbud.go.id setidaknya ada tiga kawasan yang menjadi fokus utama, yaitu kawasan Astara (Asia Tenggara), Aspasaf (Asia, Pasifik, dan Afrika), serta Amerop (Amerika dan Eropa). Fasilitasi pembelajaran BIPA di negara-negara tersebut juga memiliki beberapa skema seperti pengiriman tenaga pengajar secara langsung dari Indonesia, pengajar lokal, pengajar PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh/Daring), bahkan juga pengajar untuk diplomat.
Saya merupakan salah satu pengajar BIPA yang pernah ditugaskan langsung oleh Kemendikbud ke negara beruang merah, yaitu Rusia dan juga mengajar BIPA daring di Austria dan Swiss, baik itu di universitas maupun di KBRI. Pemelajar asing yang belajar bahasa Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Budiawan, 2023). Bahkan hingga kini, terdapat sekitar 183 ribu lebih pemelajar yang tersebar dari berbagai negara yang belajar bahasa Indonesia, entah sebagai bahasa kedua, bahasa ketiga, dan seterusnya. Aziz (2024) juga menuturkan bahwa para pemelajar memiliki motivasi yang beragam dalam mempelajari bahasa Indonesia. Misalnya untuk melanjutkan studi akademik di Indonesia, bekerja, tujuan wisata, bahkan juga ada yang karena mempunyai pasangan orang Indonesia.
Keberagaman motivasi tersebut juga akan berimplikasi pada perbedaan metode dan tujuan pembelajaran BIPA yang akan dirancang oleh pengajar sebelum memulai pengajaran di kelas. Merujuk pada SKL BIPA yang telah disusun dan disahkan menjadi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), terdapat tujuh tingkatan kelas BIPA yang dimulai dari BIPA 1 sampai BIPA 7 di tingkat mahir. Setiap level tersebut memuat silabus dan kemampuan berbahasa Indonesia yang harus dikuasai oleh pemelajarnya masing-masing.
Dalam mengajarkan BIPA luring, saya selalu berupaya menggunakan media pembelajaran yang berada di sekitar seperti media realia, permainan tradisional, wayang, peta, benda-benda yang ada di dalam kelas, dan lain-lain. Lain halnya dengan pembelajaran daring, pengajaran berbasis teknologi melalui media interaktif permainan dapat menjadi salah satu strategi untuk meminimalisir kebosanan karena hanya menatap layar selama lebih kurang 1,5 jam dalam setiap satu pertemuan. Namun yang perlu diperhatikan dalam mengajar BIPA juga adalah seorang pengajar harus mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik dari pemelajarnya tersebut. Hal ini diperlukan untuk memastikan proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal, misalnya mulai dari pemilihan bahan ajar sampai media yang akan digunakan nantinya di dalam kelas. Meskipun mengajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, namun tentu akan ada perbedaan metode pengajaran jika pemelajarnya merupakan orang dewasa, remaja atau bahkan anak-anak.
Selain itu, perencanaan pengajaran BIPA juga tidak hanya berfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi juga terintegrasi dengan budaya Indonesia yang menjadi daya tarik yang kuat bagi pemelajar asing. Hal ini yang saya lakukan di kelas daring dan luring, contohnya dengan mengenalkan kuliner khas Indonesia dan juga mengajarkan budaya lokal seperti membatik, menari, bermain alat musik tradisional, dan lain-lain. Kusmiatun (2018) memaparkan bahwa dengan modifikasi dan variasi materi yang diajarkan dapat menambah wawasan pemelajar dari berbagai sisi, bukan hanya penguasaan tata bahasa saja.
Mayoritas para pemelajar juga mengutarakan bahwa kekayaan budaya dan keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi salah satu faktor yang memperkuat alasan mereka untuk tidak sabar berwisata ke negara Indonesia lebih dari satu kali. Keramahan orang Indonesia dan juga kelezatan makanannya juga turut membuat pemelajar BIPA ingin selalu kembali berkunjung ke Indonesia. Menurut penuturan mereka, orang asing yang datang ke Indonesia minimal menghabiskan waktu lebih dari 3 minggu dalam satu kali kunjungan, terlebih jika mereka berasal dari negara Eropa atau Amerika yang bisa menghabiskan waktu penerbangan belasan jam dari negaranya.
Konsistensi pemelajar asing yang belajar bahasa Indonesia di kelas BIPA luring atau daring selalu mereka upayakan di tengah kesibukan pekerjaan dan juga studi yang sedang ditempuh. Mereka juga sangat menghargai pengajar BIPA yang datang langsung ke negara mereka atau mengajar secara daring karena perbedaan zona waktu yang terkadang sangat jauh sehingga pembelajaran harus diselenggarakan pada tengah malam waktu Indonesia. Hal tersebut ditunjang oleh pengadaan kelas-kelas BIPA di luar negeri yang dapat terlaksana secara berkelanjutan karena dukungan dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi program BIPA dapat diselenggarakan dengan maksimal.
Upaya penginternasionalan bahasa Indonesia memang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus adanya kolaborasi dari berbagai pihak yang saling mendukung (Rohimah, 2018). Salah satu bentuk nyata implementasinya diwujudkan melalui penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO secara konsensus dalam sesi Pleno Konferensi Umum ke-42 tahun 2023 lalu di Prancis. Hal ini tentu berdampak positif pada perdamaian dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional.
Dengan semakin banyaknya orang asing mengenal Indonesia, maka akan semakin terbuka konektivitas yang luas antarbangsa. Selain itu, BIPA juga dapat memegang peranan penting sebagai penunjang keberhasilan diplomasi lunak (soft diplomacy) melalui bahasa di ranah internasional. Tentu bukan upaya yang instan untuk mencapai ratusan ribu pemelajar BIPA hingga saat ini yang pernah dan sedang mempelajari bahasa Indonesia, melainkan diperlukan kegigihan dan sinergi harmonis yang melibatkan banyak pihak di dalamnya. Oleh karena itu, pencapaian eksistensi bahasa Indonesia di mata dunia hingga sekarang patut untuk diapresiasi dan dijaga agar selalu bermartabat.