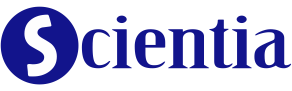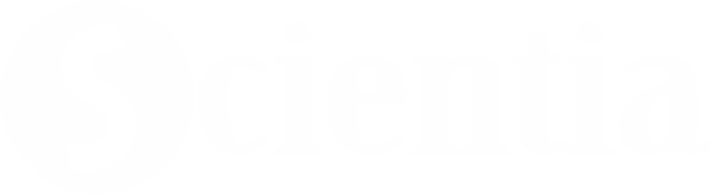Oleh: Mayang Puti Ifanny
(Mahasiswi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas)
Seiring berjalannya waktu, sastra terus saja menghadirkan energi baru yang membuat warna sastra sendiri beragam. Setiap zaman memiliki lika-liku perjalanan unik dan memberi pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Terutama bagi mereka yang senang membaca karya sastra dan merealisasikan pada kehidupan sehari-hari. Dengan susunan kata-kata terbaik yang dihadirkan pengarang dan bagaimana pengarang mampu menumbuhkan tingkat emosialitas dalam diri pembaca. Semua tergantung bagaimana sastra itu dihadirkan. Sejak Belanda menginjak tanah air, lahirlah wadah untuk sastra itu berkembang yaitu Balai Pustaka, dengan bawah tangannya Belanda, agar penulis-penulis dapat dikontrol oleh pemerintah Hindia Belanda untuk tidak mengancam pemerintahahnya.
Tentu hal tersebut membawa pengaruh besar, dicontohkan novel Siti Nurbaya, yang mengangkat cerita dengan suasana perkotaan di Padang. Tentu hal ini sudah mengangkat modernitas pada masa tersebut. Keadaan ini terus berlanjut hingga keberadaan era sastra kontekstual itu dibincangkan. Melalui sastra kontekstual memberikan pembuka jalan bagi genre sastra yang berbau daerah, kebudayaan dan identitas asli suatu bangsa untuk sampai di meja publik. Penyair asal Madura Zawawi Imron melakukan gebrakan yang mencoba menghidupakan sastra kontekstual dengan sajak-sajak yang dirangkainya. Oleh karena itu sajak-sajak Zawawi Imron patut dikuliti dalam konsep kontekstual sendiri.
Mengenal Zawawi Imron
Zawawi Imron adalah seorang penyair asal Madura, yang hidup di lingkungan pedesaan yang masih asri dan terjaga. Keinginannya untuk menulis dan menuangkan hasil pikirannya daslam bentuk sajak dimulai sejak tahun 1966. Sejak ia lahir ia tetap tinggal di desanya sendiri hingga masa pensiunnya berakhir bahkan sampai masa tuanya di tempat kelahirannya. Dengan kesetian yang begitu dalam pada tanah kelahiran, muncullah sajak-sajak yang ia buat dalam tema alam dan sekitarnya. Ia sering keluar masuk dusun di daerahnya. Ia perhatikan nyanyian gadis-gadis desanya saat mencari kayu bakar, di tengah belukar. Ia resapkan siul para pemanjat pohon atau percakapan orang-orang desa tentang nasib dan kepahitan hidupnya. Hasil pengamatan itu lahir atas bentuk sajak setelah melalui proses perenungan dan pengendapan (Ratih, 2016:12).
Sajak Zawawi Imron
Saat menulis sajak, Imron mengaitkan dengan lingkungan dan alam sekitar ia berada. Dibuktikan dengan judul kumpulan sajaknya yaitu Madura Akulah Lautmu (1978), Bulan Tersusuk Ilalang (1982) Madura Akulah Darahmu (1999), Semerbak Mayang (1977) dan beberapa kumpulan sajak lainnya. Berikut juga ditampilkan satu sajak yang mengandung makna tentang alam dan lingkungan Imron
Musim Labuh
jatuh gerimis musim labuh
wahai, manis!
pada wangi tanah siwalan
ada bau sendu menikam
kutatap sepi
paras ladang yang merangkum merah membasah
hanya seorang petani
menghayati hakekat sepi
di kaki bukit
ada nyanyi pilu bening
hasrat yang biru memburu wangi ke puncak bukit
cuaca dingin
mengabur bersama warna
rindu yang ungu
gerimis kembali jatuh
di sini, manis!
ada hakekat baru tumbuh
yang kurengkuh
1966
Pada sajak ini Imron mencoba menghadirkan rayuan terhadap seseorang, tetapi masih dikemas dengan kata-kata yang menggambarkan suasana perdesaannya di Madura.
Kaitan Sajak Zawawi Imron dengan Sastra Kontekstual
Arief Budiman mengatakan bahwa Sastra Kontekstual adalah sastra yang tidak mengakui keuniversalan nilai-nilai kesusastraan. Nilai-nilai sastra terikat oleh waktu dan tempat. Gagasan sastra kontekstual bukan untuk menggempur eksistensi mereka, melainkan menempatkannya dalam konteks yang sebenar-benarnya. Sastra Kontekstual juga membuka daerah-daerah kesusastraaan baru, yang selama ini tidak terlihat (Haril Heryanto, 1985). Melalui sajak-sajaknya, Zawawi Imron secara tidak langsung berhasil membuktikan ketenaran alam sekitar dan kehidupan di desanya menjadi sastra kontekstual. Bagaimana ia mengenalkan desa dan Maduranya melalui sajak, menghadirkan warna baru dalam dunia kesusastraan Indonesia.
Melalui pembahasan sajaknya tersebut pada tahun 1982, Subagio Sastrowardoyo mengulik tentang kumpulan sajak Imron, yaitu Bulan Tertusuk Lalang dan menjadi bahan perbincangan dan dijakan objek akademis (Ratih, 2016). Kekonsistenan Imron dalam menulis sajak dapat dilihat dari tema-tema yang dihadirkan dan penggunaan kata ‘Tembang’ yang sering hadir pada sajak Imron. Jika diamati sajak Imron dapat dikatakan tidak terjamah oleh perkembangan zaman dan modernitas yang tengah terjadi di segelintir penyair saat ini. Identitas diri dari seoarang Imron dapat terpancar dari sajak-sajak yang dihadirkan sehingga patut dikatakan Imron berkembang pada saat sastra kontekstual. Eksistensi sajak Imron beriringan dengan adanya perbincangan tentang sastra kontekstual.
Imron kemudian menjadi seorang penyair yang enggan berpaling dari kehidupan asalnya. Ia membuktikan bahwa dari kampung halaman sendiri dapat tercipta sajak-sajak yang epik dan mengundang pembaca untuk mengetahui tentang Madura melalui sajak-sajaknya.