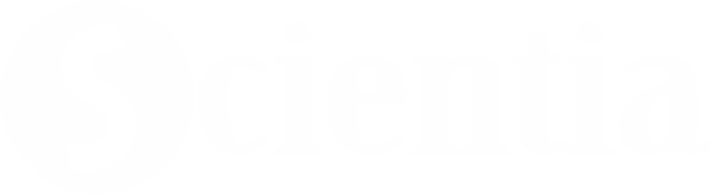Rimba Nan Tak Luko

Karya : Tasya Syafa Kamila
Mentari pagi menyelinap di antara celah dedaunan, menghangatkan tanah basah di perbukitan Minangkabau. Hutan itu, yang oleh masyarakat disebut sebagai Rimba Nan Tak Luko, adalah warisan leluhur yang tak boleh dirusak. Di dalamnya, pepohonan tua berdiri gagah, sungai mengalir jernih, dan suara burung rangkong bergema dari kejauhan.
Rafi, seorang pemuda dari Nagari Batu Manangih, berdiri di tepi hutan. Ia memandangi pohon-pohon besar yang berdiri seperti penjaga setia kampung mereka. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari kakeknya, Datuk Marajo, tentang adat Minangkabau yang menghormati alam.
“Hutan ini bukan sekadar pohon dan tanah, Nak,” kata kakeknya suatu malam. “Ini adalah ibu bagi kita. Airnya memberi kehidupan, tanahnya memberi makan, dan pepohonannya menjaga kita dari bencana.”
Tapi kini, hutan itu terancam. Sebuah perusahaan tambang ingin membuka lahan di sana. Para ninik mamak di kampung sudah berkumpul untuk membahasnya. Sebagian tergoda dengan uang yang ditawarkan, tapi sebagian lagi, seperti Datuk Marajo, bersikeras mempertahankan hutan.
“Apa pendapatmu, Rafi?” tanya kakeknya malam itu.
Rafi terdiam. Ia tahu kampung ini butuh uang, tapi ia juga tahu bahwa kehilangan hutan berarti kehilangan identitas mereka sebagai orang Minang.
“Aku ingin mencari cara lain, Kek,” jawabnya mantap.
Keesokan harinya, Rafi pergi menemui seorang tetua kampung, Mak Tuo Rajo Dirajo, yang dikenal sebagai penjaga adat dan sejarah nagari. Rumah gadangnya berdiri kokoh di tengah kampung, penuh dengan ukiran bermakna.
“Mak Tuo, bagaimana leluhur kita dulu menjaga hutan ini?” tanya Rafi.
Mak Tuo tersenyum tipis. “Dulu, ada hukum adat yang ketat. Siapa pun yang menebang pohon besar tanpa izin adat, akan dikenai sanksi. Hutan ini adalah bagian dari ulayat, tanah bersama yang tak boleh diperjualbelikan.”
Rafi mengangguk. “Tapi sekarang, perusahaan menawarkan uang yang besar. Banyak yang tergoda.”
Mak Tuo menatapnya tajam. “Apakah uang bisa menggantikan air yang bersih? Atau menggantikan udara segar?”
Rafi terdiam.
“Pergilah ke Puncak Harimau. Di sana, kau akan menemukan jawaban,” ujar Mak Tuo.
Puncak Harimau adalah tempat sakral di ujung hutan. Konon, leluhur pertama kampung mereka bermeditasi di sana sebelum mendirikan nagari
****
Pagi-pagi buta, Rafi berangkat. Ia ditemani oleh sahabatnya, Yuda, seorang pemuda yang juga mencintai alam.
Perjalanan ke Puncak Harimau tidak mudah. Mereka melewati sungai berbatu, mendaki bukit terjal, dan menembus lebatnya hutan. Suara burung dan gemericik air menjadi musik alami sepanjang perjalanan.
Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Pak Lurah yang sedang berburu ikan di sungai dengan jala kecil.
“Kalian mau ke Puncak Harimau?” tanyanya heran.
“Iya, Pak. Kami ingin melihat sendiri bagaimana hutan ini sebenarnya,” jawab Rafi.
Pak Lurah menghela napas. “Kalau perusahaan itu masuk, sungai ini akan kering. Ikan-ikan ini akan hilang.”
Mendengar itu, Rafi semakin yakin bahwa hutan ini harus dilindungi.
Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Puncak Harimau. Dari sana, terlihat hamparan hijau tak berujung. Matahari senja mewarnai langit dengan jingga keemasan.
“Inilah yang kita pertaruhkan,” kata Yuda lirih.
Setelah kembali dari perjalanan, Rafi mengumpulkan para pemuda dan ninik mamak yang masih peduli dengan hutan. Mereka berdiskusi, mencari cara agar kampung tetap sejahtera tanpa harus merusak alam.
“Aku punya ide,” kata Rafi. “Bagaimana jika kita kembangkan ekowisata? Kita buat perjalanan ke Puncak Harimau seperti yang kita lakukan, tapi untuk wisatawan. Kita juga bisa buat produk berbasis hutan yang ramah lingkungan.”
Beberapa orang setuju, tapi ada juga yang ragu.
“Itu butuh waktu, Rafi. Sementara tambang memberi uang cepat,” kata seorang mamak.
“Tapi uang cepat juga bisa cepat habis. Kalau hutan hilang, kita kehilangan segalanya,” sahut Rafi tegas.
Dengan bantuan Mak Tuo dan Datuk Marajo, Rafi mulai menggerakkan kampung. Mereka membersihkan jalur menuju Puncak Harimau, mendirikan homestay berbasis rumah gadang, dan mulai mengenalkan budaya Minang kepada wisatawan.
Ketika perusahaan tambang datang untuk menandatangani kontrak, mereka dikejutkan dengan perlawanan dari masyarakat.
“Kami tidak menjual hutan ini,” kata Datuk Marajo tegas.
“Kami sudah punya rencana lain,” tambah Rafi, sambil menunjukkan proposal ekowisata mereka.
Melihat itu, perusahaan akhirnya mundur. Mereka tahu tanpa persetujuan ninik mamak dan masyarakat, mereka tak bisa berbuat apa-apa.
Beberapa tahun kemudian, Rafi melihat kampungnya berkembang dengan cara yang tak merusak alam. Wisatawan datang, menikmati keindahan alam Minangkabau dan belajar tentang adatnya. Masyarakat tetap sejahtera, tanpa harus kehilangan warisan leluhur.
Suatu malam, di bawah sinar bulan, Datuk Marajo menepuk bahu Rafi.
“Kau telah menjaga amanah, Nak. Alam ini adalah pusaka kita. Dan kau telah memastikan ia tetap tak luko.”
Rafi tersenyum. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tapi ia telah mengambil langkah pertama untuk menyelamatkan tanah kelahirannya.
Tentang Penulis
 Tasya Syafa Kamila adalah seorang yang selalu berusaha untuk belajar dan berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, ia sangat menikmati berinteraksi dengan berbagai orang dan memahami perspektif mereka. Minat Tasya sangat luas, mulai dari membaca hingga traveling, ia memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia penulisan. Sejak SMP, ia sudah terpesona dengan kekuatan kata-kata. Ia percaya bahwa penulisan adalah sarana yang luar biasa untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, dan cerita, serta untuk menghubungkan kita dengan orang lain, bahkan di luar batas waktu dan ruang. Tasya sedang menempuh pendidikan di SMA Insan cendekia boarding school.
Tasya Syafa Kamila adalah seorang yang selalu berusaha untuk belajar dan berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, ia sangat menikmati berinteraksi dengan berbagai orang dan memahami perspektif mereka. Minat Tasya sangat luas, mulai dari membaca hingga traveling, ia memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia penulisan. Sejak SMP, ia sudah terpesona dengan kekuatan kata-kata. Ia percaya bahwa penulisan adalah sarana yang luar biasa untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, dan cerita, serta untuk menghubungkan kita dengan orang lain, bahkan di luar batas waktu dan ruang. Tasya sedang menempuh pendidikan di SMA Insan cendekia boarding school.
Pesan Moral untuk Menjaga Lingkungan di dalam Cerita Pendek
(Analisis Cerpen “Rimba Nan Tak Luko” Karya Tasya Syafa Kamila)
Oleh: Azwar
(Dewan Penasihat Pengurus Forum Lingkar Pena (FLP) Wilayah Sumatera Barat)
Nurgiantoro (2013) menyampaikan bahwa cerpen memiliki pesan moral di dalam ceritanya. Pesan moral merupakan amanat atau ajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita, yang berisi nilai-nilai baik untuk diteladani. Lebih jauh Nurgiantoro menyampaikan bahwa nilai moral adalah pesan yang terkandung dalam karya sastra yang diungkapkan melalui cerita, yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca.
Kreatika edisi ini menayangkan cerpen berjudul “Rimba Nan Tak Luko” karya Tasya Syafa Kamila. Cerpen ini mengisahkan perjuangan Rafi, seorang pemuda dari Nagari Batu Manangih, dalam mempertahankan hutan adat “Rimba Nan Tak Luko” dari ancaman eksploitasi perusahaan tambang. Sejak kecil, Rafi tumbuh dengan ajaran kakeknya, Datuk Marajo, yang menanamkan nilai bahwa hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Minangkabau.
Ketika perusahaan tambang menawarkan uang besar kepada masyarakat untuk membuka lahan, terjadi perdebatan di antara ninik mamak. Sebagian tergoda oleh keuntungan cepat, sementara yang lain ingin mempertahankan hutan sebagai warisan leluhur. Rafi pun berusaha mencari solusi alternatif agar kampung tetap sejahtera tanpa harus menghancurkan alam.
Dengan petunjuk dari Mak Tuo Rajo Dirajo, Rafi melakukan perjalanan ke Puncak Harimau, tempat sakral yang memberi pemahaman lebih dalam tentang pentingnya menjaga hutan. Sepulangnya, ia mengusulkan pengembangan ekowisata sebagai solusi berkelanjutan. Setelah kerja keras menggerakkan masyarakat, akhirnya kampung menolak investasi tambang dan memilih jalur pariwisata ramah lingkungan.
Melalui kegigihan dan kecintaannya terhadap tanah kelahiran, Rafi berhasil membuktikan bahwa kesejahteraan bisa dicapai tanpa harus merusak alam. Hutan tetap lestari, dan Nagari Batu Manangih berkembang dengan cara yang selaras dengan adat dan budaya Minangkabau.
Cerpen karya Tasya Syafa ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan cerpen ini adalah pertama, tema yang kuat dan relevan dengan masa sekarang.
Cerpen ini mengangkat isu lingkungan yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama tentang konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Pesan moralnya jelas: kesejahteraan bisa dicapai tanpa merusak alam.
Kedua, penggambaran budaya Minangkabau yang kental. Penulis berhasil menyajikan kearifan lokal Minangkabau, mulai dari konsep tanah ulayat, peran ninik mamak, hingga struktur sosial dalam mengambil keputusan. Ini memberikan pembaca wawasan tentang bagaimana adat dan tradisi masih berperan dalam kehidupan masyarakat Minang.
Ketiga, karakter yang kuat dan inspiratif. Rafi digambarkan sebagai sosok pemuda yang berpikir kritis dan berani mencari solusi alternatif. Ia bukan sekadar menolak tambang, tetapi juga menawarkan solusi konkret, yaitu ekowisata, yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya idealis tetapi juga visioner.
Keempat, alur yang mengalir dan membangun ketegangan. Cerpen ini memiliki struktur yang rapi dengan konflik yang jelas. Perjalanan Rafi ke Puncak Harimau menjadi titik balik yang memperdalam makna perjuangannya.
Kelima, deskripsi alam yang indah. Penulis berhasil menggambarkan keindahan hutan dan kearifan lokal dengan detail yang imersif, membuat pembaca seolah-olah bisa melihat dan merasakan suasana hutan Minangkabau.
Sementara itu kekurangan cerpen ini adalah pertama, konflik yang terlalu mudah diselesaikan. Perjuangan Rafi melawan perusahaan tambang terasa sedikit terlalu mudah. Dalam realitas, perusahaan biasanya memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Perlawanan masyarakat terhadap eksploitasi alam sering kali menghadapi tantangan yang lebih berat, seperti intimidasi atau perpecahan di antara warga.
Kedua, minimnya pengembangan karakter pendukung. Beberapa tokoh pendukung seperti Yuda, Pak Lurah, dan beberapa ninik mamak hanya muncul sekilas tanpa pengembangan lebih dalam. Padahal, jika mereka diberi peran lebih aktif, cerita bisa terasa lebih hidup dan dinamis.
Ketiga, potensi konflik internal yang kurang digali. Di dalam kampung, pasti ada individu yang lebih keras menolak atau lebih gigih mendukung tambang. Namun, dalam cerpen ini, pertentangan internal kurang dieksplorasi secara mendalam. Jika ada tokoh antagonis yang lebih kuat, misalnya seorang pemuka adat yang ngotot mendukung tambang, konflik bisa lebih dramatis.
Keempat, akhir yang terlalu idealistis. Walaupun endingnya memberi harapan, keberhasilan ekowisata dalam waktu singkat terasa sedikit utopis. Perubahan sosial dan ekonomi biasanya membutuhkan waktu lebih lama dan menghadapi berbagai tantangan.
Cerpen ini memiliki pesan moral yang kuat dan menggambarkan budaya Minangkabau dengan indah. Namun, agar lebih realistis dan emosional, konflik bisa dibuat lebih kompleks dengan memperdalam tantangan yang dihadapi Rafi, baik dari pihak perusahaan maupun masyarakatnya sendiri. Dengan begitu, perjuangan Rafi akan terasa lebih dramatis dan berkesan.
Agar lebih menarik, cerpen “Rimba Nan Tak Luko” ini bisa menambahkan beberapa hal. Pertama meningkatkan ketegangan dalam konflik. Ketegangan dapat diciptakan dengan menambahkan tekanan dari pihak Perusahaan. Hal ini bisa dengan menambahkan karakter perwakilan perusahaan yang mencoba membujuk atau bahkan mengintimidasi warga, misalnya dengan janji-janji manis atau ancaman terselubung. Selain itu juga bisa membuat konflik internal lebih tajam. Hal ini dengan menciptakan dramatisasi dengan tidak semua warga langsung setuju dengan Rafi. Bisa ada tokoh yang keras kepala mendukung tambang karena kebutuhan ekonomi mendesak, sehingga Rafi harus meyakinkan mereka dengan cara yang lebih emosional.
Kedua, mengembangkan Karakter Pendukung. Yuda sebagai pendamping aktif bisa diberikan peran lebih besar, misalnya awalnya ia skeptis terhadap perjuangan Rafi, tapi kemudian berubah pikiran setelah ikut perjalanan ke Puncak Harimau. Selain itu perlu menghadirkan tokoh antagonis di kampung. Hal ini dengan adanya seorang mamak atau pemimpin yang sangat pro-tambang, sehingga Rafi harus berdebat atau menghadapi perlawanan dari dalam.
Ketiga, memperdalam perjalanan ke Puncak Harimau. Tambahkan rintangan fisik atau mistis: Bisa ada hujan deras, pohon tumbang, atau mitos tentang roh penjaga hutan yang membuat perjalanan lebih dramatis. Selain itu dengan meningkatkan emosi dan refleksi Rafi. Di puncak, bisa ada momen reflektif di mana Rafi semakin yakin dengan misinya setelah melihat keindahan alam atau mengalami pengalaman spiritual.
Selain itu, untuk beberapa hal yang bisa ditambahkan agar cerita ini semakin menarik adalah dengan membuat akhir yang lebih realistis dan emosional. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat perjuangan lebih Panjang. Alih-alih langsung sukses, mungkin ada penolakan awal dari masyarakat atau proses pengembangan ekowisata yang lambat.
Bisa juga dengan menambahkan konsekuensi bagi Perusahaan. Bisa ada surat keputusan pemerintah yang melarang penambangan karena tekanan dari warga, atau perusahaan mundur karena kampanye besar-besaran. Terkhir cerpen ini bisa semakin menarik jika penulis memberikan epilog yang menyentuh. Misalnya, bertahun-tahun kemudian, Rafi melihat hutan tetap lestari dan anak-anak kampungnya kini tumbuh dengan kesadaran menjaga alam. (*)
Tentang Kreatika
 Kolom ini diasuh oleh FLP Sumatera Barat bekerja sama dengan Scientia.id. Kolom ini diperuntukkan untuk pemula agar semakin mencintai dunia sastra (cerpen dan puisi). Adapun kritik dalam kolom ini tidak mutlak merepresentasikan semua pembaca. Kirimkan cerpen atau puisimu ke karyaflpsumbar@gmail.com.
Kolom ini diasuh oleh FLP Sumatera Barat bekerja sama dengan Scientia.id. Kolom ini diperuntukkan untuk pemula agar semakin mencintai dunia sastra (cerpen dan puisi). Adapun kritik dalam kolom ini tidak mutlak merepresentasikan semua pembaca. Kirimkan cerpen atau puisimu ke karyaflpsumbar@gmail.com.
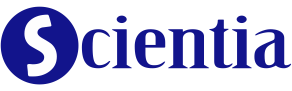










![Ketua Dewan Pengarah (SC) Muda Golkar Sumbar ke-XI, Hafrizal Okta Ade Putra (kiri) didampingi Sekretaris SC, Andi Mastian di Kantor Golkar Sumbar. [foto : sci/yrp]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/06/IMG202506281054392-350x250.jpg)