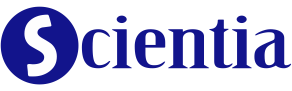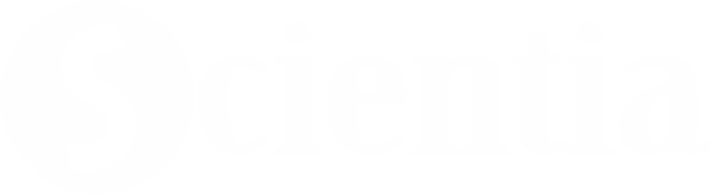Oleh: Hasbi Witir
(Mahasiswa Sastra Indonesia FIB Universitas Andalas)
Banyak dari kita mungkin beranggapan bahwa sejarah sastra Indonesia modern dimulai dari karya-karya Balai Pustaka seperti Azab dan Sengsara karya Merari Siregar atau Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Karya-karya ini yang sering dianggap sebagai tonggak utama dari lahirnya sastra Indonesia modern. Walhasil, banyak orang yang menganggap ruang lingkup sastra Indonesia modern hanya sampai pada persoalan adat dan kawin paksa saja. Namun, di balik itu terdapat “harta karun” dalam sastra di luar Balai Pustaka yang sempat terpendam selama puluhan tahun yang disebut “sastra liar” pada masa itu dan merupakan bab penting yang jarang dibicarakan, yaitu Sastra Peranakan Tionghoa atau Sastra Cina Peranakan.
Salah satu masalah terbesar dalam penulisan sejarah sastra Indonesia adalah pandangan yang terlalu “sempit”. Sastra Indonesia modern sering hanya dikaitkan dengan Balai Pustaka dan tema-tema yang sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda, seperti konflik adat, kawin paksa, atau benturan antara generasi tua dan muda. Karya-karya yang menantang atau menyinggunng isu politik, perlawanan, serta kritik sosial akan dianggap “berbahaya” dan tidak diakui sebagai bagian dari sastra resmi. Akibatnya, banyak penulis peranakan Tionghoa yang justru dilupakan. Padahal, mereka turut menanamkan semangat nasionalisme melalui tulisan-tulisan yang menggugah kesadaran dan kemanusiaan.
Sastra peranakan Tionghoa telah lebih dulu menyoroti isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Karya-karya seperti Drama di Boven Digoel oleh Kwee Tek Hoay atau Merah oleh Lim Khing Hoo mengangkat perlawanan terhadap kolonialisme dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Ironisnya, karya-karya berani ini dulu dianggap “tidak pantas” untuk diakui sebagai bagian dari sejarah sastra Indonesia.
Dalam perkembangannya, karya-karya ini tidak lagi terbatas pada lingkungan Tionghoa saja. Setelah semangat kebangkitan nasinoal menyebar pada tahun 1920-an, para penulis peranakan mulai menulis kisah tentang kehidupan pribumi, perjuangan rakyat, dan isu-isu sosial yang lebih luas. Hal ini membuat karya mereka terasa lebih realistis, dan dekat dengan pembaca. Bahkan, beberapa di antaranya mengangkat kisah nyata yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat pada saat itu dengan tema-tema yang dianggap tabu oleh Balai Pustaka seperti pemogokan buruh, pemberontakan 1926, hingga pengasingan ke Boven Digoel justru menjadi inspirasi utama mereka.
Salah satu contoh yang menarik adalah novel Drama di Boven Digoel karya Kwee Tek Hoay, yang mengangkat kisah para tahanan politik di tanah pembuangan, karya ini menjadi bukti keberanian sastra peranakan Tionghoa dalam menyoroti kenyataan pahit kolonialisme. Bahkan, Pramoedya Ananta Toer pernah menyebutnya sebagai bagian dari “sastra asimilatif” karena menghubungkan semangat nasionalisme dengan pengalaman yang multietnis.
Namun, temuan paling unik datang dari dunia sastra daerah, khususnya sastra Sunda. Liang Liji menemukan sebuah novel berbahasa Sunda berjudul Tjin Nio atawa Istri Sadjati di Medan Perang Tiongkok–Japan (1938) karya A.S. Tamoewiredja, yang diduga merupakan penulis peranakan Tionghoa. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta dan perjuangan di tengah perang Tiongkok-Jepang, tetapi juga menyelipkan pesan kemanusiaan dan nilai-nilai keislaman yang kental di dalamnnya. Tokoh utamanya, Ma Tjoe Tiong dan Tjin Nio yang digambarkan memiliki semangat juang dan keteguhan moral. Mereka berjuang bukan hanya demi cinta, tetapi juga demi kemerdekaan dan keadilan. Bahkan, Tamoewiredja menggambarkan peran wanita sebagai sosok pemberani yang menentang ketidakadilan dan kekerasan perang.
Dari segi bahasa, karya ini menggunakan bahasa Sunda populer, jauh dari gaya formal dan “asing” yang biasa digunakan Balai Pustaka. Hal ini menunjukkan bahwa sastra peranakan Tionghoa turut memberi kontribusi dalam perkembangan bahasa dan memperkaya khazanah sastra Indonesia melalui keberagaman bentuk dan latar budaya. Bahasa yang digunakan dalam karya-karya mereka cenderung lebih dekat dengan keseharian, dan berani keluar dari aturan yang ditetapkan oleh lembaha kolonial.
Sastra peranakan Tionghoa juga penting dilihat dalam konteks sosial dan politik zamannya. Pada masa itu, menjadi penulis yang mengkritik kolonialsime bukanlah hal yang mudah. Setiap kata yang ditulis bisa dianggap sebagai ancaman besar terhadap stabilitas politik Hindia Belanda. Namun para penulis menulis dengan penuh kesadaran dan keberanian. Karya mereka tidak hanya menjadi bentuk hiburan, tetapi juga sarana pendidikan dan kebangsaan secara terselubung. Mereka menyuarakan keadilan, penderitaan, penindasan, dan harapan akan kemerdekaan, jauh sebelum proklamasi 1945 dikumandangkan. Dari pembahasan tersebut, jelas bahwa sastra peranakan Tionghoa bukanlah bagian pinggiran atau buangan, melainkan mata rantai penting dalam sejarah sastra Indonesia modern. Ia memperlihatkan bahwa sastra Indonesia tumbuh dari berbagai budaya dan pengalaman sosial, bukan dari satu sumber saja.
Sudah saatnya kita meninjau ulang sejarah sastra Indonesia dengan pandangan yang lebih inklusif dan objektif. Mengakui keberadaan sastra peranakan Tionghoa berarti mengakui bahwa sastra Indonesia lahir dari keberagaman budaya dan etnis. Melalui karya-karya sastra peranakan Tionghoa, kita dapat melihat cermin dari semangat nasionalisme, kemanusiaan, dan keindonesiaan yang tumbuh dari akar yang multikultural. Dengan menggali kembali “harta karun” ini, kita sebenarnya sedang memperkaya pemahaman tentang identitas bangsa Indonesia.
Sastra peranakan Tionghoa adalah saksi bisu dari masa ketika suara-suara minoritas terpinggirkan dan diabaikan, namun mereka tetap berani menulis demi menyuarakan kebenaran. Mereka mungkin tidak di bahas secara rinci atau bahkan tidak dimasukan dalam buku pelajaran, tetapi melalui tulisan mereka kita bisa melihat semangat nasionalisme dan kemanusiaan tumbuh dari akar yang sangat beragam.
Kini, ketika dunia sastra semakin terbuka, inilah saat yang tepat untuk menyalakan kembali obor yang pernah padam. Mungkin benar, seperti kata Liang Liji bahwa menggali sastra peranakan Tionghoa berarti menggali harta karun yang telah lama terkubur dan sebuah harta yang tak ternilai karena di dalamnya tersimpan potret ke-Indonesiaan yang sesungguhnya.