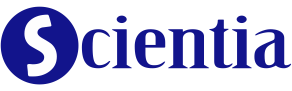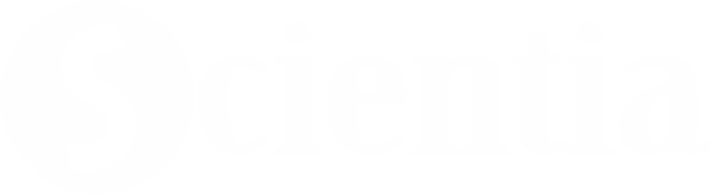Oleh: Raisa Tanjia Ayesha Noori
(Mahasiswa S2 Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas)
Peraturan Daerah (Perda) sering kali dianggap sebagai instrumen teknis semata. Padahal, di balik teks hukum yang kaku tersebut terdapat relasi kuasa yang menentukan bagaimana masyarakat hidup secara teratur, bahkan diserang secara turun-temurun. Contoh konkretnya adalah Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang mengatur pemerintahan Nagari di Minangkabau, Sumatera Barat.
Pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Van Dijk digunakan untuk menganalisis artikel yang berjudul “Power in the Discourse of West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari” yang ditulis oleh Elly Delfia dan Arimi yang terbit dalam Currciula Journal of Teaching and Learning Volume 9 Nomor 3 Tahun 2024. Artikel tersebut membahas bagaimana Perda Nagari tidak hanya beroperasi sebagai regulasi administratif, tetapi juga mengandung refleksi dominasi pemerintah daerah, ideologi tertentu, serta memiliki sisi diskriminatif terhadap masyarakat nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat adat Minangkabau yang unik dan berdiri di atas filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, sebuah prinsip yang meyakinkan bahwa adat berpijak pada syariat Islam dan syariat Islam bersumber pada Al-Qur’an. Namun, ketika Nagari diatur melalui perda, pemerintah provinsi memegang kewenangan yang seharusnya dimiliki masyarakat adat. Perda ini bukan hanya sekadar peraturan administrasi, tetapi berperan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan negara atas masyarakat adat.
Pendekatan AWK van Dijk memungkinkan untuk menilai bagaimana bahasa dalam teks perda atau teks hukum lainnya dapat menjadi alat hegemoni, kontrol halus melalui pernyataan-pernyataan yang ada. Model AWK van Dijk dilakukan dalam bentuk analisis struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.
Analisis struktur makro terhadap Perda Nagari yang dilakukan Delfia dan Arimi (2024) menunjukkan bahwa masalah utamanya adalah pembatasan otoritas Nagari oleh pemerintah provinsi. Gubernur dan DPRD Sumatera Barat lebih dominan dalam proses penetapan pembatasan tersebut, seperti penetapan definisi Nagari dan pembatasan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN), misalnya dengan hanya mengizinkan KAN untuk memilih Kapalo Nagari sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan sentralisasi kekuasaan di mana Nagari yang seharusnya otonom, malah dikendalikan oleh kekuasaan yang lebih tinggi.
Pada level superstruktur, bagian-bagian teks perda dirancang untuk menekankan dominasi negara. Lambang Burung Garuda yang mengandung butir Pancasila di bagian kepala perda bukan sekadar formalitas belaka, melainkan simbol hegemoni negara yang menegaskan bahwa Nagari tunduk pada kekuasaan negara atau pemerintah pusat.
Frasa-frasa seperti “Menimbang” dan “Mengingat” digunakan untuk memberi kesan bahwa perda ini sah, legal, dan logis, sementara kata “MEMUTUSKAN” dan “MENETAPKAN” yang ditulis kapital menegaskan otoritas mutlak pemerintah. Tanda tangan Gubernur dan Sekretaris Daerah di halaman penutup berperan sebagai penegas validasi kekuasaan, seperti jika tanpa persetujuan mereka, aturan ini tidak dapat berlaku.
Pada level struktur mikro, analisis sintaksis dan semantik membongkar bagaimana halusnya kekuasaaan berfungsi. Dari sudut semantik, filosofi Adat-Syarak dipakai sebagai dasar Nagari. Namun, secara praktis, perda justru melemahkan otoritas adat dengan mengatasnamakan “penyelarasan” Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada sebuah asumsi tersembunyi bahwa dengan memaknai Undang-Undang Desa, perda seolah harus diproduksi, sedangkan secara benar ini merupakan suatu keputusan politik untuk mengendalikan Nagari.
Dari sudut sintaksis, penulisan kopula “adalah” pada kalimat definisi seperti “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat” menunjukkan bahwa pemerintah provinsi yang menetapkan seperti apa Nagari yang seharusnya atau Nagari yang ideal, bukan masyarakat adat itu sendiri. Klausa panjang yang terkait dengan kata “bahwa” juga menyebabkan peraturan tersebut terkesan absolut dan tidak dapat diganggu gugat. Bentuk-bentuk kekuasaan yang dikenal dalam perda ini adalah diskriminasi, ideologi, dan dominasi. Pemerintah provinsi mengatur Nagari melalui batasan dan definisi kemampuan dan wewenang yang dimiliki, sedangkan simbol Burung Garuda dan kalimat negara serta adat syarak digunakan untuk menyatukan agama dan ideologi negara. Hal itu menyamarkan hak otonomi adat.
Hal yang paling mengejutkan adalah terjadinya diskriminasi terselubung, misalnya, penempatan posisi Bundo Kanduang (perempuan adat) di bagian paling bawah dalam struktur otoritas yang ada dalam teks perda. Padahal, masyarakat Minangkabau bersifat matrilineal yang seharusnya memberi posisi tinggi bagi perempuan atau setidaknya setara dengan laki-laki. Bundo Kanduang adalah pelindung dan penganut adat. Ada juga praktik peliyanan (the others), dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyebut dirinya sebagai we “kita”, sedangkan masyarakat dibentuk/disebut sebagai them “mereka”, yang menguatkan adanya sekat atau perbedaan kelas sosial karena kekuasaan.
Terakhir, Perda Nagari Sumatera Barat bukan hanya peraturan teknis, tetapi arena pertarungan wacana antara kekuasaan negara dan otonomi masyarakat adat berlangsung di sana. Melalui bahasa, simbol dan struktur teks, pemerintah provinsi mengonsolidasikan hegemoninya, tetapi dengan pemahaman tentang hubungan kekuasaan ini.
Masyarakat Nagari dapat lebih kritis untuk mempertanyakan mengapa otoritas adat harus dibatasi dan menuntut pengakuan yang setara bagi posisi Bundo Kanduang dalam teks perda, serta menolak wacana yang menempatkan Nagari sebagai objek, bukan subjek hukum. Dari artikel tersebut, kita dapat melihat hukum tidak pernah tetap netral dan selalu memihak. Pertanyaannya adalah hukum memihak kepada siapa?