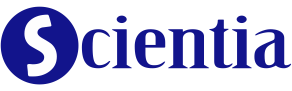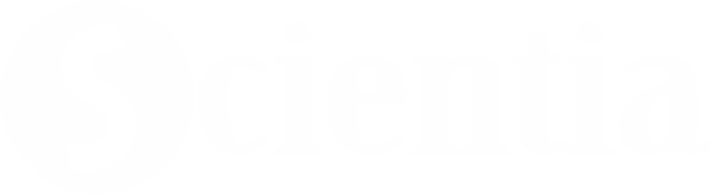Oleh: Ghina Rufa’uda
(Mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas)
Dan yang paling berat bagi semua orang tua dan keluarga aktivis yang hilang adalah: insomnia dan ketidakpastian (Leila S. Chudori dalam Laut Bercerita)
Tragedi 1998 menjadi salah satu bab gelap dalam sejarah Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap. Runtuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menjadi momentum besar dalam perjalanan bangsa, namun di balik kata “reformasi” yang lantang digaungkan, banyak anak bangsa yang harus menanggung luka mendalam, kehilangan, bahkan kematian. Hingga saat ini, peristiwa tersebut masih diselimuti misteri, tidak diketahui siapa dalang dibalik kekerasan dan penghilangan paksa, serta para korban yang tak kunjung ditemukan.
Generasi muda masa kini tampak semakin jauh dari ingatan sejarah tersebut. Banyak yang tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban, bagaimana tragedi itu bermula, dan apa saja yang sebenarnya terjadi masa itu. Hal ini bukan semata-mata karena kelalaian, melainkan karena adanya upaya sistematis untuk menghapus jejak peristiwa: berita disensor, suara dibungkam, dan kebenaran disembunyikan. Akibatnya, generasi setelahnya kehilangan arah dan pengetahuan tentang bagian penting dari sejarah bangsa.
Melalui novel Laut Bercerita yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) pada 1 Oktober 2017, Leila S. Chudori berupaya menghidupkan kembali memori kolektif tragedi tersebut. Novel itu disambut dengan antusias masyarakat luas, bahkan hingga Juli 2024 telah mencapai cetakan ke-100 yang menandakan betapa kuatnya resonansi kisah yang diangkat.
Laut Bercerita berfokus pada peristiwa penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis tahun 1998. Selain menggambarkan perjuangan mahasiswa melawan ketidakadilan, Leila juga menyoroti penderitaan keluarga korban yang ditinggalkan, nasib para mahasiswa yang diculik dan disiksa, serta keteguhan keluarga dalam mencari kebenaran dan keadilan atas hilangnya orang-orang tercinta.
Untuk memahami karya ini secara mendalam, digunakan pendekatan strukturalisme genetik yang dikemukakan oleh Lucien Goldmann. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis unsur-unsur pembangun cerita secara internal, tetapi juga hubungan sosial yang melatarbelakangi lahirnya karya tersebut. Menurut Goldmann, karya sastra adalah ekspresi pandangan dunia dari subjek transindividual. Oleh karena itu, karya sastra tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuknya.
Pandangan ini menegaskan bahwa kajian sastra tidak cukup berhenti pada analisis unsur intrinsik, seperti tema, tokoh, atau alur saja, tetapi juga perlu meninjau unsur ekstrinsik yang membangun karya tersebut. Dengan demikian, teori strukturalisme genetik memandang karya sastra sebagai hasil interaksi kompleks antara pandangan pengarang terhadap kehidupan dan struktur sosial yang melingkupinya.
Novel Laut Bercerita diawali dengan prolog yang dituturkan oleh tokoh utama, Biru Laut, yang tengah mengalami penyekapan. Dalam keadaan mata tertutup kain, tangan diborgol, dan tubuh penuh luka, ia dibawa oleh sejumlah orang ke tengah laut. Besi pemberat diikatkan pada tubuhnya, menandakan kematian telah menantinya di dasar laut. Kisah selanjutnya bergerak mundur melalui alur kilas balik (flashback). Narasi dimulai dengan kalimat.
“Bapak, Ibu, Asmara, Anjani, dan kawan-kawan… dengarkan ceritaku…”
Sebuah panggilan dari Laut yang sudah tiada, menandakan kisah yang ia sampaikan berasal dari masa lalu. Cerita dimulai pada tahun 1991 dan bergerak maju secara tidak linier hingga 1998. Perpindahan waktu yang dinamis ini menegaskan bahwa tahun 1998 menjadi pusat dari seluruh peristiwa penting yang menggambarkan puncak perlawanan terhadap rezim Orde Baru.
Biru Laut digambarkan sebagai mahasiswa Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada yang sangat mencintai dunia literasi. Ia banyak membaca karya-karya besar , seperti Pramoedya Ananta Toer, Tan Malaka, Marx, Laclau, dan Ben Anderson. Kecintaan pada sastra dan filsafat membentuk kesadaran kritis terhadap situasi sosial-politik di masa itu. Bersama rekan-rekannya, ia aktif dalam kelompok diskusi dan pergerakan mahasiswa bernama Winatra, yang berfokus pada penyebaran gagasan-gagasan perlawanan melalui pamflet, tulisan, dan advokasi masyarakat, terutama petani di daerah Blangguan.
Aktivitas tersebut membuat mereka menjadi target pengawasan militer dan intelijen. Untuk menghindari penangkapan, mereka harus berpindah tempat secara berkala. Namun, tekanan dan ancaman tidak berhenti. Laut dan teman-temannya dituduh melakukan makar terhadap pemerintah. Pada tahun 1998, mereka akhirnya ditangkap, diinterogasi secara brutal, dan mengalami penyiksaan. Dari peristiwa itu, 13 aktivis dinyatakan hilang dan 9 lainnya dikembalikan dalam kondisi trauma berat. Tidak ada kejelasan mengenai kriteria siapa yang dilepaskan dan siapa yang dihilangkan selamanya.
Nasib Biru Laut berakhir tragis. Tubuhnya yang penuh luka dibuang ke laut, disertai tawa dingin para pelaku penyiksaan. Adegan ini menjadi simbol keheningan dan kebungkaman dalam sejarah bangsa, di mana suara-suara keadilan dibungkam tanpa belas kasihan. Bagian kedua novel beralih ke sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut. Tokoh ini menjadi representasi bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Cerita yang berfokus pada tahun 2000 hingga 2007 menampilkan perjalanan Asmara sebagai dokter forensik yang berusaha menelusuri keberadaan kakaknya dan rekan-rekan aktivis lainnya bersama Komisi Orang Hilang.
Asmara digambarkan sebagai sosok kuat, tegas, dan penuh empati. Melalui dirinya, pembaca diajak menyelami penderitaan batin keluarga korban yang terus menunggu kepulangan orang yang mereka cintai tanpa kepastian. Mereka menunggu di antara harapan dan keputusasaan, hidup dalam bayang-bayang kehilangan yang tak pernah selesai. Meskipun investigasi tidak pernah menemukan titik terang, semangat Laut tetap hidup melalui pesan-pesannya. Ia pernah berkata,
“Jangan lelah mencari terang dalam gelap, dan jangan sampai tenggelam dalam kekelaman. Gelap adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Dalam setiap gelap, selalu ada cahaya, meski hanya secercah di ujung lorong. Jangan biarkan kekelaman menguasai kita, apalagi menguasai Indonesia.”
Kata-kata ini menjadi inti moral dan ideologis novel, menggambarkan perjuangan untuk tetap berharap di tengah keputusasaan. Untuk mengenang dan menuntut keadilan, Asmara dan keluarga korban rutin mengikuti Aksi Kamisan, sebuah aksi diam di depan Istana Negara setiap hari Kamis. Mereka mengenakan pakaian dan payung hitam sebagai simbol duka dan perlawanan. Aksi ini menjadi bentuk nyata perlawanan terhadap lupa, serta seruan agar negara tidak menutup mata terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Leila S. Chudori membangun karakter dalam novel dengan sangat kuat dan realistis. Biru Laut ditampilkan sebagai sosok idealis yang mencintai sastra sekaligus berani memperjuangkan keadilan. Asmara Jati digambarkan rasional namun berhati lembut, mewakili suara nurani keluarga korban. Tokoh-tokoh pendukung seperti Sunu, Alex, Mas Gala, Kinan, Bapak, Ibu, Naratama, dan lainnya turut memperkuat dinamika cerita dan memperkaya lapisan emosional novel ini.
Latar tempat dalam Laut Bercerita mencakup berbagai lokasi penting seperti rumah hantu Seyegan Pelem Kecut, Bulaksumur, Blangguan, Pulau Seribu, Ciputat, Istana Negara, Padang, hingga New York. Rentang waktu cerita berlangsung antara tahun 1991 hingga 1998, sedangkan latar sosial mencerminkan kondisi Indonesia pada masa itu yang tengah berada dalam situasi ekonomi dan politik yang kacau akibat pemerintahan yang otoriter.
Dari sisi sudut pandang, novel ini menggunakan dua narator: orang pertama pelaku utama melalui tokoh Biru Laut, dan orang pertama pelaku tambahan melalui Asmara Jati. Penggunaan dua sudut pandang ini memperlihatkan dua perspektif berbeda, dari korban yang menghilang dan dari keluarga yang kehilangan. Fakta kemanusiaan yang tergambar dalam Laut Bercerita mencerminkan realitas sosial Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Novel ini menampilkan dua jenis fakta, fakta individu dan fakta sosial.
Fakta individu tercermin melalui tokoh Biru Laut yang digambarkan sebagai mahasiswa Sastra Inggris yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia literasi. Kegemarannya membaca dan menulis membuatnya memahami situasi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada masa itu. Melalui interaksinya dengan karya-karya pemikir besar, Biru Laut membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan yang terjadi di negaranya. Sebagai mahasiswa yang aktif berdiskusi dan berkegiatan sosial, ia menjadikan sastra sebagai medium untuk menyuarakan kebenaran dan perlawanan terhadap rezim yang menindas.
Fakta sosial dalam novel ini memperlihatkan kondisi masyarakat Indonesia pada periode 1990-1998 yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan otoriter dengan dominasi militer yang kuat. Situasi ekonomi yang terpuruk akibat krisis moneter serta kekacauan politik yang meluas menimbulkan keresahan di berbagai lapisan masyarakat. Dalam kondisi demikian, muncul berbagai gerakan mahasiswa yang menuntut perubahan dan menentang sistem yang korup. Tokoh Biru Laut dan kelompok Winatra yang ia ikuti menjadi representasi dari semangat perlawanan tersebut. Aktivitas mahasiswa di masa itu tidak berjalan mudah. Pemerintah menanggapi kritik dengan kekerasan, intimidasi, dan pembungkaman. Banyak aktivis diculik, disiksa, bahkan dihilangkan secara paksa. Fakta ini sejalan dengan nasib tragis yang dialami Biru Laut dalam novel. Ia menjadi korban kekejaman aparat negara hanya karena memperjuangkan kebenaran.
Selain itu, Leila S. Chudori juga menyoroti fakta sosial lainnya, yakni perjuangan keluarga korban dalam mencari keadilan. Para keluarga tidak berhenti menuntut kejelasan mengenai nasib orang-orang tercinta yang hilang. Aksi-aksi yang mereka lakukan, seperti Aksi Kamisan di depan Istana Negara, menjadi simbol perlawanan terhadap lupa dan ketidakpedulian negara. Aksi ini dilakukan secara damai setiap hari Kamis dengan atribut serba hitam sebagai lambang duka dan solidaritas. Bentuk perjuangan seperti ini juga pernah dilakukan oleh para ibu di Argentina dan Cile yang memperjuangkan nasib anak-anak mereka karena penghilangan paksa oleh rezim diktator. Dalam perspektif strukturalisme genetik, fakta-fakta tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil ciptaan dari individu atau kelompok tertentu yang disebut sebagai subjek kolektif. Dalam Laut Bercerita, subjek kolektif dapat dibagi menjadi dua kelompok utama.
Pertama, para aktivis mahasiswa, diwakili oleh tokoh Biru Laut dan rekan-rekannya dalam kelompok Winatra dan Wirasena. Mereka merupakan generasi muda yang sadar politik, kritis, dan berani menyuarakan kebenaran di tengah represi negara. Melalui diskusi, penulisan pamflet, dan aksi sosial, mereka menciptakan realitas sosial berupa gerakan perlawanan yang menjadi simbol perjuangan mahasiswa Indonesia pada akhir masa Orde Baru.
Kedua, keluarga korban, yang diwakili oleh Asmara Jati dan orang tua Biru Laut. Mereka menjadi subjek kolektif yang terus mempertahankan ingatan akan peristiwa kelam itu. Keluarga-keluarga ini menjalin hubungan emosional dan sosial satu sama lain, berbagi rasa kehilangan, dan melakukan aksi bersama untuk menuntut keadilan. Dalam konteks teori Goldmann, keluarga para korban turut membentuk struktur sosial baru: kelompok masyarakat yang menolak diam dan berjuang melawan pelupaan sejarah.
Sementara itu, pandangan dunia pengarang (world view) terefleksi melalui dua tokoh utama: Biru Laut dan Asmara Jati. Pandangan dunia Biru Laut menggambarkan keberanian, idealisme, dan kepedulian terhadap situasi bangsa. Sebagai mahasiswa yang mencintai sastra, Biru Laut melihat dunia melalui nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan berpikir. Ia meyakini bahwa perubahan sosial hanya dapat terjadi jika masyarakat berani bersuara. Tindakannya yang berani melawan kekuasaan menjadi cerminan dari pandangan dunia pengarang tentang pentingnya intelektualitas yang berpihak pada kebenaran.
Pandangan dunia Asmara Jati berbeda namun saling melengkapi. Ia mewakili suara mereka yang ditinggalkan, keluarga korban yang terus memperjuangkan keadilan tanpa kekerasan. Melalui sosok Asmara, Leila ingin menunjukkan bentuk perlawanan yang penuh keteguhan, kesabaran, dan cinta kasih. Aksi Kamisan yang diikutinya adalah simbol harapan agar bangsa tidak melupakan masa lalu dan terus mencari kebenaran meski waktu terus berjalan.
Selain dua tokoh tersebut, pandangan dunia Leila S. Chudori juga tampak dalam penggambaran sikap tokoh-tokohnya terhadap dunia sastra. Biru Laut yang tumbuh sebagai pembaca karya-karya besar sejak kecil merepresentasikan pandangan pengarang bahwa sastra memiliki kekuatan untuk membentuk kesadaran sosial. Melalui literasi, seseorang dapat memahami realitas secara lebih mendalam dan menolak tunduk pada ketidakadilan.
Dengan demikian, pandangan dunia yang ditampilkan dalam novel ini merefleksikan keprihatinan pengarang terhadap kondisi sosial, politik, dan kemanusiaan Indonesia pada akhir abad ke-20. Leila menolak sikap pasif dan menegaskan pentingnya keberanian moral untuk menghadapi ketidakadilan, baik melalui tindakan aktivis seperti Biru Laut maupun keteguhan hati seperti Asmara Jati.
Secara keseluruhan, Laut Bercerita tidak hanya menghadirkan kisah tragis tentang penghilangan paksa aktivis, tetapi juga menjadi bentuk perlawanan terhadap lupa. Melalui perpaduan antara struktur naratif, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang, novel ini memperlihatkan fungsi karya sastra sebagai sarana kritik sosial dan refleksi kemanusiaan yang mendalam.