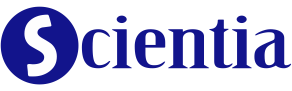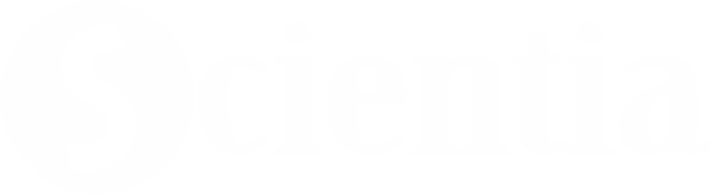Oleh: M.Subarkah
(Mahasiswa Prodi S2 Linguistik Universitas Andalas)
Bahasa daerah adalah warisan yang tidak hanya layak dikenang, tetapi harus dihidupkan kembali. Ia seperti taman yang pernah subur namun kini mulai ditinggalkan. Bila tidak segera dirawat, satu per satu bunga di dalamnya akan layu dan hilang tanpa jejak. Oleh sebab itu, menjaga bahasa daerah berarti menanam kembali benih kebanggaan pada tanah budaya kita sendiri.
Langkah pertama menjaga bahasa daerah adalah menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa daerah bukan beban masa lalu, melainkan penanda keberagaman yang memperkaya bangsa. Indonesia memiliki lebih dari tujuh ratus bahasa daerah, Setiap satunya adalah potongan mozaik identitas nasional. Jika satu bahasa daerah punah, satu warna dalam mozaik itu ikut hilang, membuat lukisan kebangsaan kita semakin pudar.
Masyarakat, terutama generasi muda, perlu melihat bahasa daerah bukan sebagai sesuatu yang kuno atau terbatas, melainkan sebagai ruang ekspresi dan kreativitas. Banyak kata dalam bahasa lokal memiliki nuansa makna yang unik, bahkan tak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain, misalnya kata nyesek dalam bahasa Jawa yang menggambarkan perasaan sesak di dada karena sedih, atau mangidah dalam bahasa Batak yang berarti menasihati dengan kasih. Kata-kata semacam ini menunjukkan kekayaan rasa yang khas pada tiap kebudayaan.
Revitalisasi bahasa daerah dapat dilakukan melalui jalur seni dan media populer. Musik tradisional bisa dikemas ulang dalam genre modern; film pendek dan drama lokal bisa diproduksi dalam dialek daerah; buku cerita anak dapat ditulis dengan dwibahasa bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dengan cara ini, bahasa lokal tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh di ruang-ruang baru yang dekat dengan kehidupan generasi digital.
Peran komunitas dan lembaga budaya menjadi kunci. Di berbagai daerah, sudah mulai muncul gerakan kecil: kelas belajar bahasa daerah gratis, festival sastra lokal, atau akun media sosial yang mengajarkan kosakata bahasa daerah dengan cara lucu dan interaktif. Upaya-upaya sederhana seperti ini sesungguhnya adalah bentuk cinta yang nyata terhadap bahasa daerah. Cinta yang tidak bising, tetapi bekerja pelan-pelan menyelamatkan suara-suara tua dari sunyi yang abadi.
Pemerintah pun memiliki tanggung jawab moral dan historis dalam menjaga warisan linguistik ini. Perlindungan bahasa daerah bukan hanya tugas dinas pendidikan atau kebudayaan, melainkan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan identitas bangsa. Program revitalisasi harus disertai dukungan nyata: pelatihan guru, pengembangan buku ajar, digitalisasi manuskrip lama, hingga pemberian penghargaan bagi penutur aktif dan pelaku budaya. Bahasa tidak akan hidup hanya dengan aturan, melainkan dengan ekosistem yang memeliharanya.
Bahasa sebagai warisan jiwa, setiap bahasa adalah rumah bagi jiwa. Di dalamnya, manusia menemukan makna, rasa, dan arah. Ketika bahasa daerah kita punah, sesungguhnya yang hilang bukan sekadar kata-kata, melainkan juga cara kita memahami kehidupan. Bayangkan, betapa sepinya dunia ketika kata-kata penuh cinta, doa, atau petuah leluhur hanya tinggal teks tanpa penutur.
Setiap bahasa adalah jiwa yang hidup dalam bunyi. Karena di balik setiap sapaan lembut ibu kepada anaknya, di balik setiap cerita rakyat yang diceritakan di bawah cahaya lampu minyak, tersimpan warisan yang membentuk siapa kita hari ini. Bahasa daerah bukan masa lalu yang harus dilupakan, melainkan akar yang menegakkan pohon masa depan kita sebagai bangsa. Ketika bahasa daerah mulai sunyi, kita tidak boleh diam. Kita harus menjadi suaranya dalam ucapan, dalam tulisan, dalam karya, dan dalam cinta. Karena selama masih ada yang menuturkannya dengan hati, bahasa daerah akan tetap hidup, berdenyut, dan berbisik lembut di antara riuh dunia modern: “Aku masih ada.”
Menjaga bahasa daerah sejatinya adalah tanda cinta. Cinta kepada negeri, kepada leluhur, dan kepada masa depan. Ia adalah bentuk penghormatan kepada sejarah, sekaligus komitmen untuk terus melanjutkannya. Kita boleh maju setinggi langit, menapaki dunia global dengan teknologi dan modernitas, tetapi jangan sampai kita kehilangan tanah tempat berpijak. Sebab tanpa akar budaya, kemajuan hanyalah bangunan megah tanpa fondasi. Bahasa daerah adalah akar budaya itu yang diam, kuat, dan memberi kehidupan. Kita semua dengan cara masing-masing, memiliki tugas untuk memastikan akar budaya itu tetap hidup.