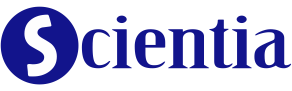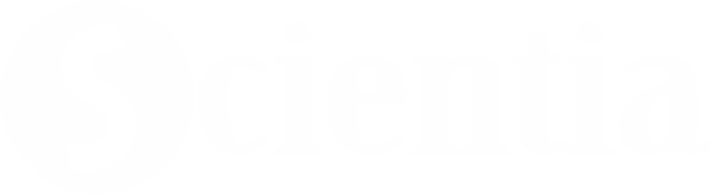Oleh: Andina Meutia Hawa
(Dosen Prodi Sastra Indonesia FIB Universitas Andalas)
Kajian ekokritik membahas hubungan antara manusia, karya sastra, dan lingkungan alam. Menurut Endraswara (2016), ekokritik atau sastra ekologis merupakan ilmu yang membahas unsur ekstrinsik karya sastra dan mendalami hubungan sastra dan lingkungannya. Oleh sebab itu, penerapan kajian ekokritik terhadap karya sastra dapat membuat pembaca memahami pesan-pesan yang disampaikan pengarang, sekaligus menambah wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan.
Di tengah munculnya kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, sastra tidak hanya hadir sebagai media hiburan, tetapi juga menjadi alat refleksi untuk meningkatkan kesadaran ekologis. Salah satu bentuk karya yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah fabel, sebuah cerita rekaan dengan tokoh-tokoh binatang yang berperilaku seperti manusia. Melalui dialog dan perilaku binatang, fabel menyampaikan pesan moral dan nilai kehidupan yang mudah dipahami, terutama oleh anak-anak (Mustikasari, 2021).
Penggunaan ekokritik dalam mengkaji karya sastra dapat menjadi alat untuk memahami dampak perusakan alam dan pentingnya pelestarian lingungan. Buku cerita Ginting und Ganteng karya Frey & Rappo (2020) merupakan salah satu contoh fabel yang memuat pesan-pesan yang menyerukan pentingnya pelestarian lingkungan. Aspek-aspek diperlihatkan melalui kisah seekor orang utan yang terusir dari habitat aslinya. Cerita ini tidak hanya mengajak pembaca memahami penderitaan mahluk hidup akibat keserakahan manusia, sekaligus menumbuhkan empati serta kesadaran menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Berikut adalah uraian aspek-aspek ekoritik dalam buku cerita Ginting und Ganteng.
Kritik terhadap Perusakan Alam
Buku cerita Ginting und Ganteng mengangkat tema eksploitasi hutan tropis oleh manusia melalui penebangan liar dan pembakaran hutan. Hal tersebut diperlihatkan pada kutipan berikut.
Suatu hari Merah mendengar suara-suara aneh di hutan, makin lama makin mendekat.
Satu persatu pohon tumbang. Terdengar suara-suara berisik. Habitat Merah dan berbagai hewan lainnya dihancurkan.
Para penebang pohon mengangkut kayu-kayu besar. Mereka kembali lagi dan terus mengangkut kayu-kayu. […]. Debu dan serbuk gergaji beterbangan di udara (Frey & Rappo, 2020: 20 – 24).
Kutipan di atas menggambarkan proses perusakan hutan dengan cara penebangan liar di hutan tropis melalui pandangan seekor orang utan, yang bernama Merah. Aktivitas yang merusak alam tidak hanya menimbulkan suara-suara bising dan gaduh, tetapi juga merusak habitat makhluk hidup. Penebang hutan yang mengangkut lebih banyak kayu merupakan bentuk eksploitasi alam, dan didorong oleh keserakahan manusia. Dalam kajian ekokritik, narasi ini menggambarkan kritik terhadap tindakan perusakan alam yang mengganggu keseimbangan ekologis dan mengorbakan keberlangsungan makhluk hidup lain melalui kepentingan ekonomi.
Dampak Perusakan Lingkungan terhadap Hewan Liar
Selain menggambarkan proses perusakan lingkungan melalui aktivitas penebangan liar, fabel Ginting und Ganteng (Frey & Rappo, 2020) juga mengkritik dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Hal itu terlihat melalui kutipan di bawah ini.
Merah bergerak dari tempat persembunyiannya. Tiba-tiba hutan yang sudah rusak itu dibakar habis oleh manusia. Hewan-hewan yang bisa terbang ataupun berlari, menyelamatkan diri mereka masing-masing: burung, rusa, harimau, babi hutan, gajah, dan orang utan. Semuanya ikut terbakar. Untungnya, Merah masih sempat menyelamatkan diri (Frey & Rappo, 2020: 27).
Penggambaran bahwa hutan yang sudah habis itu dibakar oleh manusia merupakan kritik tajam terhadap tindakan manusia yang tidak hanya merusak, tetapi juga menganggu keseimbangan ekosistem. Kajian ekokritik menjadi media penyampaian kritik terhadap perusakan alam melalui karya sastra. Dalam hal ini sastra tidak hanya dipandang melalui aspek estetika, tetapi juga dapat menjadi alat resistensi terhadap ketidakseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Karya sastra dapat “menyuarakan” suara-suara makhluk hidup lain yang terbungkam.
Hewan-hewan menyelamatkan diri merupakan penggambaran ketakutan serta insting bertahan dari situasi yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Pembakaran hutan menyebabkan kepunahan sebagian besar hewan yang tinggal di sana. Namun, keberadaan Merah yang masih bertahan menjadi simbol harapan, serta dorongan untuk melakukan pelestarian hutan.
Kritik terhadap Penanaman Perkebunan Sawit
Merah terus berjalan. Kemana lagi ia harus mencari makanan dan tempat tinggal? Ia terus berjalan sampai menemukan sebuah kebun sawit besar yang dulunya merupakan hutan tropis. Di sana tumbuh pohon-pohon sawit. Dalam beberapa tahun ke depan, pohon-pohon itu akan berbuah dan akan diolah menjadi minyak sawit. Merah memetik sebuah buah sawit muda, tetapi ia tidak menyukai rasanya (Frey & Rappo, 2020: 28).
Kebun sawit besar yang dulunya merupakan hutan tropis menggambarkan proses peralihan lahan hutan menjadi industri monokultur, yaitu kebun sawit. Kutipan di atas sekaligus merupakan kritik atas dampak destruktif peralihan hutan menjadi kebun sawit yang menyebabkan hewan liar kehilangan habitat, makanan, dan hak hidup. Kehilangan tempat tinggal meyebabkan Merah tersesat dan terancam kelaparan. Peralihan hutan tropis menjadi kebun sawit tidak lebih baik karena tidak mampu menggantikan hutan sebagai sumber makanan dan tempat tinggal hewan.
Harapan melalui Konservasi
Di area konservasi, Merah dirawat. Luka-lukanya dibersihkan. Kondisi Merah perlahan pulih. Hari demi hari Merah semakin terbiasa dengan kehidupan barunya di area
konservasi. Di sini, orang-orang utan yang menjadi korban akibat ulah manusia dirawat dan dipersiapakan untuk kembali ke alam liar (Frey & Rappo, 2020: 34).
Kutipan di atas menggambarkan fase pemulihan Merah setelah mengalami luka akibat ulah manusia. Area konservasi menjadi simbol harapan bagi pemulihan dan kelangsungan hidup orang utan. Penggambaran Merah yang dirawat dan dibersihkan luka-lukanya, serta dipersiapkan untuk kembali ke alam liar merupakan wujud tanggung jawab manusia untuk memberpaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan. Dalam hal ini terjadi pergeseran peran manusia, dari menjadi pelaku perusakan menjadi penyelamat. Selain itu, kutipan di atas juga menyiratkan pesan bagi untuk melakukan tindakan pemeliharaan hutan yang menjadi habitat asli hewan liar, sekaligus upaya pemulihan keseimbangan ekosistem.
Pemulihan dan Kehidupan Kembali di Alam Liar
Di tengah jejak kerusakan yang ditinggalkan manusia, alam masih menyediakan ruang bagi penyembuhan dan harapan. Kutipan mengenai pelepasan Merah, Ginting dan Ganteng kembali ke alam liar menggambarkan hal tersebut.
Ginting dan Ganteng sudah cukup besar untuk meninggalkan area konservasi orang tuan. Mereka rencananya akan dibawa ke tempat pelepasan bersama Merah. […]. Di sinilah tempat itu berada, sebuah area dimana para orang utan dipersiapkan untuk kembali hidup di hutan liar. Merah dan Si Kembar menghabiskan beberapa minggu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Ketiganya kerap dikunjungi oleh orangutan yang sudah hidup di alam liar. […]. Suatu pagi, gerbang terbuka. Jalan masuk ke hutan liar terlihat jelas. Merah yang melangkah menuju hutan. Ganten mengikutinya, namun Ginting masih ragu-ragu (Frey & Rappo, 47 – 55).
Kutipan di atas menggambarkan tahapan yang dilalui dalam pelepasan Merah, Ginting, dan Ganteng ke alam liar. Ketiganya dipindahkan dari area konservasi orang utan ke area pelepasan, di mana mereka harus melalui proses penyesuaian sebelum menjalani kehidupan di alam liar. Di area pelepasan, ketiganya beradaprasi dan berinteraksi dengan orang-orang utan lain. Ketika gerbang menuju hutan dibuka, Merah terlihat lebih yakin untuk memasuki hitan liar, dan Ganteng mengikutinya. Adapun Ginting masih ragu. Kalimat tersebut merupakan cara masing-masing orang utan dalam menghadapi perubahan. Ada yang cepat, ada pula yang lambat. Gerbang terbuka merupakan simbol harapan dan pemulihan, serta menunjukkan bahwa proses kembali ke alam yang tidak selalu mudah.
Dengan demikian, fabel Ginting und Ganteng merupakan media penyampaian kritik ekologis kedua pengarang terhadap perusakan alam akibat penebangan liar, pembakaran hutan, dan penanaman kebun sawit. Melalui sudut pandang seekor orang utan, cerita ini menggambarkan dampak destruktif akibat ulah manusia yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Kisah Ginting und Ganteng juga menghimbau pembaca melalui pesan-pesan pelestarian alam dan rehabilitasi orang utan di area konservasi. Pelepasan Merah, Ginting dan Ganteng menjadi simbol pemulihan ekologis sekaligus upaya manusia untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya. Aspek ekokritik lainnya juga terlihat pada pesan-pesan untuk meningkatkan kesadaran ekologis dan peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem.