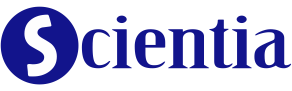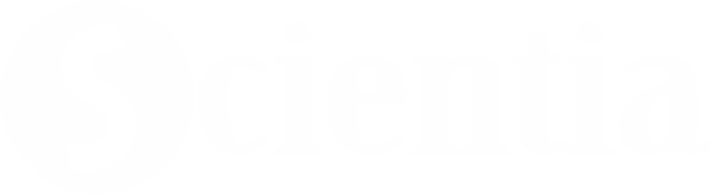Ada kalanya disebut naskah, ada kalanya disebut manuskrip. Dua kata ini menjadi perhatian saya saat mengikuti serangkaian kegiatan Sumatera Manuscripts Festival (Sumfest) yang dilaksanakan 21—30 Juli 2025 oleh Universitas Andalas bekerja sama dengan SOAS University London dan Museum Adityawarman. Di antara rangkaian kegiatan tersebut, saya mengikuti tiga kegiatan, yaitu seminar internasional “Khazanah Iluminasi Naskah Sumatera dan Potensi Pengembangan”, masterclass “Membaca dan Mengkaji Naskah Sumatera”, serta Lokakarya Naskah Sumatera.
Dari tema-tema kegiatan yang diangkat, sudah tampak variasi penyebutan antara naskah dan manuskrip. Secara kuantitaif, kata naskah menjadi kata terbanyak yang dipakai, termasuk dalam paparan selama seminar, masterclass, dan lokakarya. Hal ini sebanding dengan pengalaman saya membaca dan berdiskusi tentang naskah kuno. Kata naskah menjadi diksi yang paling sering disebut. Hanya sesekali memang terdengar manuskrip. Ini tak lepas dari objek yang dibicarakan bahwa naskah adalah hasil karya masa lampau yang ditulis dengan tulisan tangan, baik di kertas, lontar, maupun daluang. Robson (1994) dalam Prinsip-prinsip Filologi Indonesia menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam naskah itu adalah naskah yang sudah berumur, sekurang-kurangnya lima puluh tahun (Lihat juga Zuriati, 2014, Dunia Pernaskahan Nusantara).
Secara etimologi, kita bisa menelusuri dari mana kata naskah masuk ke dalam bahasa Indonesia dan dari mana pula kata manuskrip masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata naskah dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa Melayu, yaitu naskah. Sama halnya dengan penggunaan kata naskah dalam bahasa Malaysia. Hal ini tercatat melalui A Malay-English Dictionary (Wilkinson, 1959) yang menjelaskan bahwa kata naskah dalam bahasa Melayu berasal dari bahasa Arab. Dalam kamus tersebut, tertulis bahwa naskah adalah exemplar ‘eksemplar’; prototype ‘prototipe’; original text ‘teks asli’; of the ‘authorized version’ of the old Testament ‘Taurat yang sah’; dan of the text and copyright of a work bought for publication ‘teks dan hak cipta karya yang dibeli untuk publikasi’.
Sementara itu, kata manuskrip merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris. Baik di Indonesia maupun di Malaysia, kata manuskrip dipakai untuk menjelaskan makna yang sama dengan naskah. Istilah manuscript (s) berasal dari bahasa Latin, yaitu codicesmanu scripti yang berarti ‘buku-buku yang ditulis dengan tangan’ (Lihat Zuriati, 2014). Mulyadi dalam (1994) dalam Kodikologi Melayu di Indonesia menyatakan bahwa manuscript (s) berasal dari kata manu (dari manus) ‘tangan’ dan scriptusx (dari dari scribere) ‘menulis’.
Dari etimologi itu, tampak bahwa orang-orang Indonesia sejak dahulu begitu mahir menulis tangan. Zuriati (2014) menjelaskan bahwa sampai tahun 2008, tradisi menulis dengan tangan ini, dengan menggunakan aksara lama, masih ada di Minangkabau dan bahkan juga di Bali. Di Minangkabau, para penyalin menggunakan aksara Arab dan aksara Arab-Melayu, seperti Syekh Imam Maulana Abdul Munaf Amin di Surau Batang Kabung, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Namun, tahun 2006 beliau meninggal dunia. Yang kemudian masih lanjut menulis adalah Angku Abdul Hadi di Surau Nagari Matan Panjang, Sijunjung, Sumatera Barat. Beliau masih menulis dan menyalin naskah hingga tahun 2008, seperti naskah-naskah keagamaan.
Dunia digital pada hari ini justru “membunuh” kemampuan kita dalam menulis dengan tangan. Cobalah ambil sebuah pena, lalu menulislah selama mungkin. Salinlah tulisan dalam buku-buku yang ada di sekitar kita atau tulislah sebuah cerita—tanpa henti—sekitar 15 menit. Dalam waktu 2-3 menit menulis, kita pasti sudah mulai merasakan tangan kaku, keram, dan sakit. Sebuah kondisi yang akan menyebabkan banyak orang berhenti dan meninggalkan kebiasaan menulis, lalu beralih mengambil handphone atau laptop untuk menuliskan gagasan.
Di kampus-kampus di beberapa perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebenarnya masih ada dosen yang mewajibkan para mahasiswa menulis tugas dengan tulisan tangan, misalnya Prof. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pernah bercerita melalui media sosial bahwa para mahasiswa di Harvard University diminta oleh beberapa dosen untuk mengerjakan tugas dengan menggunakan tulisan tangan. Menulis dengan tangan membuat materi yang ditulis melekat di dalam ingatan dibandingkan hanya diketik atau disalin dari satu sumber ke sumber lain melalui microsoft word. Ketika disalin secara digital, kita cenderung membaca cepat, menyalin, dan kemudian tugas selesai. Materi pun lewat begitu saja.
Namun, jika hal ini diminta kepada mahasiswa Indonesia, mengerjakan tugas yang diminta dengan tulisan tangan, yang dikumpulkan adalah (1) tulisan tangan yang kadang tidak bisa dibaca; (2) tulisan tangan yang sangat pendek, yang kadang setengah halaman double folio adalah beberapa kalimat yang sengaja ditulis dengan ukuran huruf yang besar dan jarak yang sangat lebar; dan (3) tulisan tangan yang antara satu kalimat dengan kalimat yang lain tidak bisa dipahami apa maksudnya.
Seperti tidak ikhlas menulis, seperti tidak mau mendapatkan ilmu. Namun, kalau nilai sudah keluar, mereka dengan rasa tidak malu bertanya, “Mengapa nilai saya A-, Bu, padahal saya berhak mendapat nilai A karena sudah mengerjakan semua tugas”. Padahal, nilai yang diakumulasi tidak hanya dari jumlah tugas yang dikerjakan, tetapi juga melihat bagaimana tugas yang dikerjakan, apakah mereka mampu memahami materi yang disampaikan dengan sangat baik.
Barangkali itulah sebabnya ketika mahasiswa diminta menjelaskan sesuatu, seperti teori yang dipakai dalam menganalisis data penelitian, mereka tidak bisa menjelaskan secara runut. Bagaimana mungkin bisa? Ketika dalam menulis, mereka sudah tidak runut berpikir, tentu dalam berbicara juga tidak akan runut dan tidak sistematis. Padahal, dalam sejarah penulisan dan penyalinan naskah-naskah kuno, kita memiliki tradisi menyalin dan menulis yang sangat baik.
Sebagai pengajar, saya tetap optimis masih ada generasi muda yang mau menulis dengan baik, baik dengan tulisan tangan maupun dengan tulisan digital. Dalam masterclass naskah kuno kemarin misalnya, dalam 15 menit, para peserta yang tergabung ke dalam satu tim berhasil mentransliterasi 1—2 halaman manuskrip yang disajikan. Pada awal kegiatan, Dr. Mulaika Hijjas sebagai peneliti utama naskah Sumatera meminta kepada peserta agar pelan-pelan saja melakukan transliterasi. Namun, mereka dengan semangat dan begitu cepat mentransliterasi naskah dari Arab Melayu menjadi Latin. Bahkan, ketika ada kata yang sulit, mereka segera mengambil kertas dan menulis huruf asalnya dari bahasa Arab. Kondisi ini menggambarkan hal yang berbeda saat Dr. Mulaika Hijjas membuka masterclass dan mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada lagi generasi muda yang tertarik dengan naskah kuno atau manuskrip. Namun, kenyataannya masih ada. Para peserta masterclass merupakan generasi muda yang tertarik itu.
Melihat kemampuan para peserta membaca Arab Melayu dan mentransliterasikan ke dalam bahasa Latin, dunia manuskrip seperti mendapat berkah. Ternyata masih (akan) ada generasi muda yang mampu membaca manuskrip Sumatra dan melakukan transliterasi dalam 10—25 tahun mendatang. Meskipun tidak lagi menulis dengan tangan, setidaknya mereka akan menunjukkan kepada kita pengetahuan apa yang terdapat dalam naskah atau manuskrip tersebut.
Dari kegiatan Sumfest ini, saya mendapatkan satu buah catatan. Kurikulum yang ada di Fakultas Sastra atau Fakultas Ilmu Budaya seharusnya menjadikan bahasa Arab dan bahasa Arab Melayu sebagai salah satu mata kuliah wajib dengan langsung meminta mahasiswa mentransliterasi naskah-nakah kuno. Prof. Pamono dari Universitas Andalas mencatatat bahwa saat ini sudah ada 1.235 naskah kuno yang terdigitalisasi, tetapi baru 50 naskah yang ditransliterasi. Bahkan, Iik Hidayati dari Universitas Lancang Kuning menjelaskan dari 250-an naskah Melayu yang terdokumentasi, saat ini baru dua naskah yang ditransliterasi. Ini sebuah catatan sekaligus peluang agar kita kembali mewarisi tradisi menyalin dan menulis dari naskah atau manuskrip.