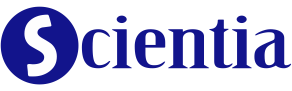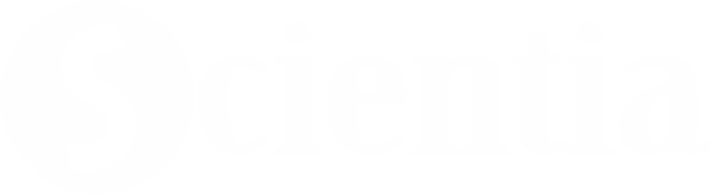Oleh: Nikicha Myomi Chairanti
(Mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Universitas Andalas)
Cerita pendek “Seekor Beras dan Sebutir Anjing” karya Eka Arief Setyawan mengisahkan tentang seorang walikota, Willem Sambar, yang akan mengakhiri masa jabatannya dalam tiga bulan. Sambar membuat sebuah peraturan baru dengan hukuman yang bahkan lebih berat daripada vonis hukuman bagi yang terbukti melakukan korupsi. Inilah keunikan cerpen ini. Seorang yang dikenal cerdas dan visioner namun kaku menetapkan aturan kosakata baru dari “seekor” untuk benda dan “sebutir” untuk hewan. Apa yang membuat sang walikota menetapkan aturan absurd tersebut? Sebuah kebijakan aneh bisa saja lahir dari kepala yang dingin, atau dari hati yang terluka. Dalam cerpen ini, yang kedua tampaknya lebih masuk akal.
Cerpen tersebut tidak hanya menyajikan kisah tentang aturan bahasa yang aneh, tetapi juga menyimpan luka lama yang perlahan terkuak di balik kekuasaan. Setelah menetapkan aturan aneh di penghujung masa jabatannya, mengganti penggunaan kata “seekor” untuk benda dan “sebutir” untuk binatang, Willem Sambar, Walikota Negeri Alur, memicu kekacauan di tengah masyarakat. Aturan ini tidak main-main. Siapa pun yang melanggarnya akan dipenjara minimal sepuluh tahun. Masyarakat mulai ketakutan, saling curiga, hingga hampir seluruh guru bahasa, sebagian anggota dewan hingga berbagai lapisan masyarakat pun ditangkap karena salah ucap.
Cerita pun perlahan mengungkap sisi kelam di balik keputusan sang walikota. Lewat alur kilas balik, pembaca diajak menyelami masa kecil Sambar yang penuh kekerasan. Ia dihina, dipukul, dan kerap dipanggil “seekor anjing” oleh ayahnya sendiri. Kenangan ini menancap dalam, dan ketika ia dewasa serta berkuasa, trauma itu muncul kembali dalam bentuk keputusan yang tampaknya konyol, namun menyimpan makna balas dendam yang dalam. Puncaknya terjadi ketika masyarakat turun ke jalan menuntut keadilan. Di tengah kekacauan itu, Sambar akhirnya bersuara, “Saya sudah menunaikan seluruh dendam saya.” Kalimat ini seperti membuka kunci utama cerita bahwa di balik aturan bahasa, tersembunyi luka yang tak pernah benar-benar sembuh.
Namun, kisah ini tidak berhenti pada kericuhan dan kebijakan aneh semata. Justru yang paling mengguncang adalah luka tersembunyi yang menjadi akar dari segalanya. Dalam teori psikoanalisis, Sigmund Freud membagi struktur kepribadian manusia menjadi tiga elemen: id, ego, dan superego. Id merupakan bagian terdalam dan paling primitif yang berisi dorongan naluriah, seperti agresi, keinginan, atau dendam. Ego berfungsi menengahi antara dorongan id dan kenyataan luar, sedangkan superego mencerminkan nilai moral dan hati nurani. Freud menjelaskan, “The ego represents what may be called reason and common sense, in contrast to the id, which contains the passions” (Freud, 1923: 15).
Freud juga menyatakan bahwa pengalaman traumatis di masa kecil yang tidak terselesaikan akan ditekan ke alam bawah sadar (repression), tetapi suatu hari bisa muncul kembali dalam bentuk tindakan yang tak disadari secara logis, seperti pelampiasan (displacement). Psikolog sastra Suwardi Endraswara menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa, “Tokoh yang memiliki trauma masa kecil sering menunjukkan pelampiasan ketika dewasa. Bentuk pelampiasan ini dapat dianalisis dengan melihat id-nya yang tertindas sejak kecil” (Endraswara, 2008: 23).
Dari sinilah, pembaca bisa memahami bahwa keputusan absurd Willem Sambar bukan semata-mata soal bahasa, melainkan hasil dari luka batin yang dalam. Kata “seekor” dan “sebutir” bukan hanya masalah gramatikal baginya, melainkan simbol trauma yang membentuk struktur id-nya sejak kecil. Ketika ia menjadi pemimpin, luka itu muncul dalam bentuk kekuasaan yang otoriter. Saat ia berkata, “Saya sudah menunaikan seluruh dendam saya,” kalimat itu menjadi bukti nyata bahwa hukum dijadikan alat pelampiasan terhadap masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai.
Cerpen ini mengajak kita melihat sisi yang sering luput: bahwa luka batin yang tidak disembuhkan bisa menjelma menjadi kekuasaan yang melukai orang lain. Dalam tokoh Willem Sambar, kita tidak hanya melihat seorang pemimpin yang membuat aturan absurd, tapi juga seorang anak yang tumbuh besar bersama trauma dan dendam yang tidak pernah benar-benar usai.
Dalam dunia nyata, mungkin tidak semua pemimpin mengubah kata “seekor” menjadi “sebutir”, tapi tak sedikit yang menjadikan kekuasaan sebagai ruang pelampiasan terhadap masa lalu yang tak selesai. Kekuasaan yang dijalankan tanpa penyembuhan batin sering kali melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, melainkan pada rasa sakit yang diwariskan. Hukum bukan alat balas dendam, hukum itu soal keadilan.
Cerpen ini bukan sekadar sindiran politik, melainkan juga pengingat diam-diam: bahwa kita harus menyembuhkan luka sebelum diberi kuasa, agar luka itu tidak menular jadi keputusan yang membebani banyak kepala. Selain itu, cerpen ini juga membuka pemikiran kita untuk melihat sisi manusiawi dari seseorang yang otoriter.