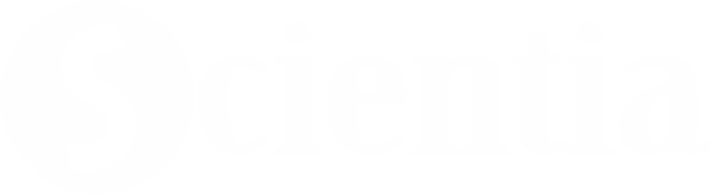Oleh: Arina Isti’anah
(Dosen Sastra Inggris, Universitas Sanata Dharma)
Perubahan iklim merupakan istilah yang terdengar akrab di telinga kita. Kita sering mendengar istilah tersebut melalui siaran berita televisi dan media sosial lain. Namun, apakah kita sudah menyadari makna dan tanda-tanda perubahan iklim di sekitar kita?
Fenomena kebakaran yang meluas di Los Angeles, California, Amerika Serikat disebut-sebut sebagai fenomena dampak perubahan iklim. Kencangnya angin di Los Angeles dianggap menjadi pemicu cepatnya api menghanguskan wilayah tersebut. Catatan menyebutkan bahwa lebih dari 23 ribu hektar telah hangus dan lebih dari 30 ribu orang telah dievakuasi (tempo.com). Kerugian ekonomi juga disebut lebih dari 250 milliar Dolar AS (Kompas.com).
Pemberitaan tentang perubahan iklim kemudian sering dikaitkan dengan kebakaran di Los Angeles. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh posisi Amerika Serikat sebagai negara besar yang dianggap maju, namun wilayah di AS ternyata juga tidak luput dari kerugian masif karena perubahan iklim. Kita diajak untuk menyadari bahwa perubahan iklim merupakan fenomena nyata yang dapat kita saksikan secara langsung, pun dampaknya yang sangat besar, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Namun, apakah memang perubahan iklim selalu ditandai dengan fenomena kebakaran yang sangat besar dan meluas, atau fenomena lain yang menyebabkan kerugian moneter yang tinggi? Apakah pemberitaan yang begitu gencar tentang perubahan iklim hanya terjadi jika negara besar saja yang mengalaminya?
Selama ini, sebagai pembaca, acapkali kita tidak terlalu sering diajak untuk terlibat dalam diskursus perubahan iklim. Dari istilahnya saja, perubahan iklim mengimplikasikan fenomena alam yang terjadi pada periode waktu tertentu dan kita terima saja sebagai fenomena yang tidak terlalu membahayakan kehidupan kita. Konstruksi perubahan iklim sebagai fenomena alam bukan tidak berhubungan dengan peran bahasa. Istilah ‘perubahan iklim’ tersebut secara terus menerus kita temukan dalam kehidupan di sekitar kita, melalui buku-buku pelajaran, surat kabar, televisi, dan media sosial. Istilah tersebut kita anggap istilah yang mapan, benar, dan tepat untuk merujuk pada fenomena krisis iklim. Jika kita bertanya pada diri sendiri, apakah ‘perubahan iklim’ itu? Mungkin kita juga masih mencari-cari jawabannya, terkait tanda-tanda dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap mitigasi perubahan iklim. Hal tersebut terjadi karena proses institusionalisasi dalam wacana publik.
Istilah ‘institusionalisasi’ perubahan iklim dalam tulisan ini merujuk pada proses pelembagaan organisasi pemerintah atau non-pemerintah, baik pada tataran nasional dan global, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perubahan iklim. Oleh karena itu, kita mungkin lebih mudah berpendapat bahwa perubahan iklim merupakan tanggung jawab BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan COP (Conference of Parties).
Penelitian tentang perubahan iklim baru-baru ini dilakukan dengan mengambil data dari pemberitaan media massa, Kompas dan Detik daring, selama 10 tahun (2013-2022). Dengan metode penelitian linguistik korpus, diketahui bahwa tema tentang mitigasi perubahan iklim masih didominasi oleh institusi global, bukan lokal atau pembaca sebagai agen penting dalam mitigasi perubahan iklim (Isti’anah, dkk., in press). Di antara institusi yang disebut antara lain “Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup”, “G20” (Group of 20 of the intergovernmental forum), “IPCC” (Intergovernmental Panel on Climate Change), “SDGs (Sustainable Development Goals)”, “ESG” (Environmental, Social, and Governance), “FAO” (Food and Agriculture Organization), “INDC” (Intended Nationally Determined Contribution), “APEC” (Asian Pacific Economic Cooperation”, dan “UNFCC” (The UN Framework Convention on Climate Change).
Organisasi-organisasi tersebut di atas, secara statistik, memiliki frekuensi tinggi dalam pemberitaan perubahan iklim selama sepuluh tahun terakhir. Hal tersebut mengartikulasikan terjadinya proses institusionalisasi atas wacana perubahan iklim. Persepsi publik tentang perubahan iklim secara terus-menerus dikonstruksi oleh media massa bahwa perubahan iklim merupakan tanggung jawab institusi global dan nasional. Dalam kajian analisis wacana kritis, proses reproduksi bahasa yang secara berulang atau repetisi merupakan salah satu wujud kebahasaan untuk membentuk ideologi (Fairclough, 2003). TIdak heran jika kita masih belum begitu familiar dengan cara-cara mitigasi perubahan iklim yang dapat kita lakukan di lingkungan terkecil kita, yakni rumah. Perilaku sederhana seperti mengurangi konsumsi produk berplastik sachet dapat kita terapkan untuk mengurangi jumlah sampah yang menjadi salah satu penyumbang terjadinya banjir.
Institusionalisasi perubahan iklim dalam media massa tidak menyiratkan wacana yang bersifat ekologis. Kita sebagai pembaca belum secara aktif dilibatkan dalam wacana perubahan iklim. Tidak heran jika kita tidak terlalu yakin dalam mengenali tanda-tanda perubahan iklim yang sebenarnya yang telah kita alami sehari-hari.
Situs web Greenpeace mencatat bahwa hujan ekstrem, kekeringan, dan tanah longsor merupakan dampak nyata dari krisis iklim, yang juga memberikan pengaruh pada kesehatan dan kenaikan harga pangan. Selain itu, prosentase penurunan produksi pangan dari sektor pertanian dan kenaikan jumlah kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan), serta meningkatnya prosentase bencana banjir yang mencapai 60% dari periode 2023 merupakan beberapa kasus dampak krisis iklim yang kita alami secara nyata (greenpeace.org).
Kita masih menganggap bahwa dampak nyata krisis iklim seperti yang dicatat oleh Greenpeace sebagai bencana alam, bukan sebagai dampak nyata krisis iklim seperti yang terjadi di Los Angeles. Oleh karena itu, sebagai pembaca dan pengguna media massa, kita bisa bersikap lebih kritis dalam menangkap krisis iklim sebagai fenomena yang memang sudah terjadi di lingkungan sekitar kita.
Media massa sebagai agen yang membentuk persepsi publik perlu meninjau kembali strategi kebahasaan dalam memberitakan krisis iklim. Alih-alih menonjolkan institusi global dalam penanganan krisis iklim, media massa dapat memberikan pajanan lebih serius terhadap narasi-narasi dampak krisis iklim yang dialami oleh kelompok rentan yang terdampak oleh mahalnya pangan dan langkanya lapangan pekerjaan karena dampak nyata krisis iklim.
Secara ekologis, media massa perlu juga mengungkap narasi-narasi positif oleh aksi nyata masyarakat dalam menjaga ekosistem. Sebagai contoh, para masyarakat pesisir menganggap laut sebagai subjek penting dalam kehidupan karena laut menghasilkan oksigen, mengatur iklim, menyediakan sumber protein, dan berperan sebagai rumah berbagai keanekaragaman hayati (greenpeace.org). Oleh karena itu, pengalaman masyarakat pesisir dalam hidup berdampingan dengan laut perlu diangkat sebagai wujud narasi positif yang dapat kita pelajari secara nyata. Perilaku masyarakat yang demikian memuat nilai lokal dan ekologis yang sepatutnya kita teladani.
Sebagai simpulan, tulisan ini mengajak pembaca dan praktisi bahasa untuk menerapkan perspektif ekologis dalam menyikapi pemberitaan tentang perubahan iklim. Kita sebagai bagian dari suatu ekosistem merupakan subjek yang secara langsung dapat berkontribusi dalam mitigasi krisis iklim, bukan hanya institusi global dan nasional yang bertanggung jawab atas krisis iklim. Media massa sebagai agen yang membentuk persepsi publik perlu menggarisbawahi peran pembaca yang seyogyanya dilibatkan secara aktif dalam wacana iklim. Institusionalisasi wacana perubahan iklim justru akan memperlebar jarak antara pembaca dengan tanda-tanda dan dampak nyata yang telah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Media massa perlu melibatkan pembaca sebagai agen mitigasi perubahan iklim dengan membangun narasi positif terkait peran masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang ekologis.
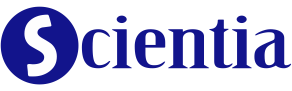








![Kantor PDAM Kota Padang.[foto : net]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/07/FB_IMG_17535045128082-350x250.jpg)