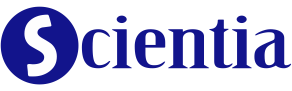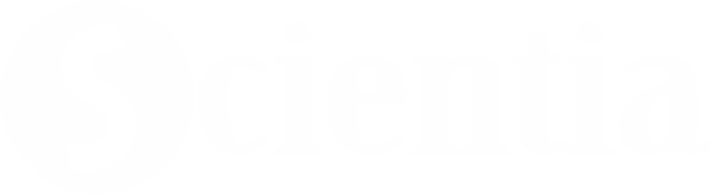Oleh: Ahmad Hamidi
(Dosen Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas)
Klaim bahwa bahasa Indonesia miskin kosakata, yang uniknya hampir selalu
diperhadapkan dengan bahasa Inggris, merupakan pernyataan berulang. Apabila yang
dilihat adalah jumlah, secara ironis, mesti diakui bahwa klaim tersebut bukanlah sinisme
atau isapan jempol belaka. Berdasarkan jumlah, kosakata bahasa Indonesia memang
lebih sedikit daripada bahasa Inggris, sebagaimana tampak pada perbandingan jumlah
entri antara Kamus Besar Bahasa Indonesia (120.639) dan Webster’s Third New
International Dictionary (470.000).
Kosakata adalah produk budaya manusia dalam melambangkan dunianya.
Kekayaan kosakata suatu bahasa bergantung pada kemampuan masyarakatnya
memersepsikan ide, lingkungan, dan alamnya. Bahasa Indonesia, sebagai contoh, kalah
jumlah kata pada bidang teknologi karena revolusi industri tidak pernah datang dari
keduniaan masyarakat Nusantara. Kita hanya konsumen atas produk budaya modern
dunia luar, lantas berkesempatan “menukar bungkus” berbagai lambang asing tersebut.
Realitas serupa terjadi pada beberapa bidang-bidang lain, baik secara konkret maupun
abstrak.
Namun, pada bidang-bidang tertentu, bahasa Indonesia punya kosakata yang
melimpah. Sebagaimana contoh yang senantiasa didapatkan mahasiswa kelas-kelas
linguistik antropologis, masyarakat Indonesia mampu mengonseptualisasikan satu
tumbuhan, dari yang masih tertanam di sawah sampai yang tersaji di atas meja makan,
dalam empat lambang monomorfemik: padi, gabah, beras, dan nasi. Oleh masyarakat
berbahasa Inggris, keempatnya dirangkum dalam satu lambang, rice—kalau bukan
memfrasakannya (rice plant, unhulled rice, husked rice, dan cooked rice). Orang
Islandia, contoh lain, menyebut konsep padi sebagai villihrísgrjón yang secara literal
berarti ‘beras liar’ (villi, ‘liar’; hrísgrjón, ‘beras’).
Masyarakat Indonesia, konon, adalah kelompok yang menjunjung tinggi
kesantunan berbahasa dan memuliakan hubungan kekerabatan. Apabila hendak
membatasi bahwa “yang asing” bukanlah “identitas kita” dan “yang lokal” adalah
“identitas kita”, undak usuk bahasa dan keberagaman peristilahan kekerabatan adalah
manifestasinya (lihat Geertz, 1960; Uhlenbeck, 1978). Untuk kedua hal tersebut,
kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada bahasa Inggris.
Kosakata bahasa Indonesia kaya bukan pada bidang teknologi informasi, filsafat, atau ilmu pengetahuan
modern, melainkan pada bidang yang merupakan dunia bagi masyarakatnya. Mereka berbahasa berdasarkan persepsi dan konseptualisasi terhadap dunianya, lainnya
hanyalah pinjaman atau padanan belaka—kita menyebutnya pengadaptasian,
penerjemahan, atau pengkreasian.
Tidak ada bahasa yang kaya sebagaimana tidak ada bahasa yang miskin
kosakata. Orang yang paham pembentukan bahasa, cara bahasa bekerja, dan
hubungannya dengan pikiran menyebutnya sebagai relativitas linguistik. “Die Grenzen
meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt”, kata Wittgenstein (1922). Anda
tidak memahami maksud kata-kata itu? Berarti itulah batas dunia Anda. Bahasa suatu
masyarakat terbatasi oleh dunianya. Masyarakat Dani di Papua, umpamanya, hanya
mengenal dua konsep warna dasar, yakni modla untuk melambangkan warna
terang/cerah dan mili untuk warna gelap/kusam (Heider, 1970) karena pengaruh
dunianya.
Tidak seperti masyarakat Indonesia yang mengenal orientasi spasial relatif kiri,
kanan, depan, dan belakang, masyarakat Aborigin-Pormpuraaw di Australia hanya
mengenal orientasi spasial mutlak, yakni kuw (barat), ungkarr (utara), kaw (timur), dan
iparr (selatan), sebagaimana arah mata angin (Boroditsky, 2009). Ketika diminta untuk
mengurutkan foto-foto yang merekam proses pertumbuhan, mereka mengurutkannya
berdasarkan orientasi timur ke barat. Apabila menghadap ke selatan, mereka
mengurutkannya dari kiri ke kanan. Apabila menghadap ke utara, mereka
mengurutkannya dari kanan ke kiri. Bagaimana ketika menghadap ke timur? Mereka
mengurutkan ke arah mendekati tubuh. Sebaliknya, ketika menghadap ke barat, mereka
mengurutkan ke arah menjauhi tubuh.
Apakah itu berarti bahasa masyarakat Aborigin-Pormpuraaw miskin karena tidak
mengenal orientasi spasial relatif sebagaimana ditemukan pada sebagian besar bahasa
di dunia? Sungguh, bahasa tidak dapat dipandang menggunakan kacamata kuda seperti
itu. Apabila dibaca secara terbalik, mereka justru memiliki kekayaan yang sama sekali
tidak dimiliki masyarakat bahasa lain karena mampu bernavigasi secara presisi di mana
pun berada. Dengan kemampuan itu, mereka tidak akan mudah tersesat di hutan.
Orang Indonesia tidak perlu memperinci salju karena terbatasi oleh dunianya
yang tidak hidup bersama salju. Bagi orang Indonesia, bagaimana pun bentuknya, di
mana pun ditemukannya, sepanjang berupa “butiran uap air berwarna putih bagaikan
kapas yang membeku”, tetap disebut salju—kata yang diserap dari bahasa Arab (لج
,ثَthalj).
Bagi masyarakat Inuktitut di Nunavik, persoalan salju tidak sesederhana itu.
Sehari-hari hidup berselimut salju, mereka perlu mengidentifikasi salju secara detail
(Krupnik, 2010; Dorais, 2020), seperti pi’rtsirpoq (drifting snow/salju melayang), maujaq
(soft snow/salju lembut), aqilokoq (softly fallen snow/salju yang turun dengan lembut),
kinirtaq (salju padat), qaneq (falling snow/salju yang sedang turun), apun (snow on the
ground/salju di permukaan), savujua’rtuang (snow block/balok salju), dan seterusnya.
Yang unik, karena mendiami pergunungan yang puncaknya bersalju, masyarakat Yali di
Angguruk, Yahukimo, punya perbedaan bentuk ungkap daripada bahasa Indonesia,
yakni lek (salju) dan lekma (salju di puncak gunung) (Zöllner & Riesberg, 2021).
Kontak bahasa memungkinkan suatu bahasa memperkaya kosakatanya. Saling
serap kata antarbahasa adalah suatu keniscayaan. Sejarah kolonialisasi dan status
sebagai bahasa internasional menyediakan fleksibilitas bagi bahasa Inggris untuk
menyerap berbagai kata dari beragam bahasa. Karena daya serap yang tinggi, bahasa
Inggris “dianggap” superior daripada bahasa-bahasa lain.
Klaim bahwa bahasa Indonesia miskin kosakata membuktikan relativitas bahasa atau
linguistik. Cara berpikir yang inferior membuat seseorang memersepsikan kalah jumlah
kosakata daripada bahasa lain sebagai bentuk kemiskinan.