
Oleh: Ahmad Hamidi
(Dosen Program Studi Sastra Indonesia FIB Universitas Andalas)
Ketika diberitakan media nasional, nama-nama tempat di geokultural Minangkabau sering berubah berdasarkan “rasa bahasa” Indonesia. Berkaitan dengan kasus intimidasi dan penangkapan warga penentang pembangunan kawasan industri dan kilang minyak kelapa sawit, Nagari Aia Bangih masuk berita nasional dengan nama Air Bangis. Pengubahan bunyi dan ortografi toponim tersebut, mengutip materi perkuliahan Prof. Multamia Lauder, dapat mencerabut nilai-nilai kultural yang membentuk sekaligus dikandungnya.
Berdasarkan bentuknya, Air Bangis merupakan pemelayutinggian Aia Bangih dalam bahasa Minangkabau. Di satu sisi, pemelayutinggian aia menjadi air dapat diabaikan karena tidak berpengaruh pada makna. Di lain sisi, pemelayutinggian bangih menjadi bangis mencerabut makna, sekaligus mencerabut nilai kultural-historis yang dikandungnya. Secara fonemis, perbedaan satu bunyi dapat membedakan makna kalau bukan melenyapkannya.
Bangih setara dengan bengis dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikannya: ‘marah; gusar’. Kalaupun dipaksakan pemelayutinggiannya, Air Bengis jauh lebih tepat secara semantis. Makna Air Bengis yang metaforis dapat dipahami. Realitas sejarah yang melatarbelakangi penamaannya dapat ditelusuri. “Air yang marah” menjelaskan bahwa daerah pesisir itu pernah diterjang gelombang besar.
Nama kecamatan yang melingkungi Aia Bangih juga dimelayutinggikan menjadi Sungai Beremas. Pemelayutinggian ini menimbulkan ambiguitas. Apakah maksudnya ber- + remas atau ber- + emas? Banyak orang beranggapan bentuk kedualah yang tepat. Padahal, tanpa dimelayutinggikan, makna dan latar belakang penamaannya sudah sangat jelas: Sungai Barameh (rameh = remas). Ber- + emas berarti keliru. Sebab, apabila maksudnya begitu, bentuknya jadi baameh (ba- + ameh), bukan barameh (ba- + rameh). Itu berdasarkan bentuk. Sekalipun begitu, kita tetap perlu membuka peluang bahwa boleh jadi pada suatu masa pernah terjadi perubahan pembunyian baameh menjadi barameh karena pengaruh situasi sosial tertentu.
Sungai Tarab, kecamatan di Kabupaten Tanah Data, contoh lain. Masyarakat setempat mengartikulasikannya Sungai Tarok. Berdasarkan KBBI, tarok sepadan dengan terap, yakni ‘pohon sukun hutan, daunnya lebar-lebar, kayunya sangat cocok untuk bahan rumah karena tahan rayap; Artocarpus blumei’. Sungai Tarok persis Citeureup bagi orang Sunda. Ketika dimelayutinggikan, tarab ibarat bangkai; bertubuh tanpa jiwa.
Pemelayutinggian toponim telah menjadi catatan sejarah tersendiri di Minangkabau. Sekalipun sebagian orang menyebutnya pengindonesiaan (lihat Hendri, 2009; Zuriati & Adilla, 2021; Asnan & Oktavianus, 2023), jejaknya sudah ada jauh sebelum bahasa Indonesia disepakati melalui Sumpah Pemuda (1928). Dalam Kaart van Midden-Sumatra Gouvernt. Sumatra’s Westkust, Zuid Ged. d.R. Sumatra’s Oostkust, Afd. Lingga, v.d. Res. Riouwen Onderh. en het Rijk Djambi, peta klasik karya J.W. Stemfoort (1885), tertulis, di antaranya, “Ajer Bangis”, “Pajakombo”, “Moengkar”, “S. Tarab”, dan “Tabet Patah”—peta-peta lain mencantumkan variasi pemelayutinggian yang berbeda. Masyarakat Minangkabau pada masa itu menganggap bahasa Melayu-Riau sebagai ragam yang lebih tinggi (Melayu Tinggi) daripada bahasa Melayu-Minangkabau (Melayu Rendah).
Gejala ini merupakan konsekuensi budaya keberlisanan lokal. Masyarakat Minangkabau saisuak mengenal bitjaro kasa dan bitjaro gadoeang, yakni dua ragam bahasa yang pemakaiannya bergantung pada situasi pertuturan dan relasi sosial antar-penutur. J.L. van der Toorn (1881), peneliti Minangkabau berkebangsaan Belanda, menjelaskan bahwa bitjaro kasa adalah ragam yang digunakan dalam situasi informal, terutama antar-penutur yang berasal dari nagari yang sama. Adapun bitjaro gadoeang adalah ragam yang digunakan dalam situasi formal dan/atau ketika berkomunikasi dengan orang-orang dari nagari luar atau orang asing.
Dalam ragam bitjaro gadoeang, orang Minangkabau terbiasa melakukan hiperkoreksi pada kata-kata tertentu (Suryadi, 2017), seperti mada yang diartikulasikan jadi madar, bana → banar, takao → terkaha, maloyo → melaya, dan bakalebuik → berkalebut. Gejala itu merembes pada pengartikulasian toponim.
Bahasa pada dasarnya adalah bunyi. Untuk kebutuhan dokumentasi, bebunyian itu dilambangkan dalam bentuk rangkaian huruf. Para ilmuwan atau pejabat Hindia Belanda pada masa itu melambangkan bunyi berdasarkan pendengarannya atas artikulasi ragam bitjaro gadoeang. Dengan demikian, tercatatlah dalam berbagai peta nama-nama tempat yang jauh dari pengartikulasian masyarakat sehari-hari. Sebagian jejaknya masih terkesan sampai kini sekalipun ragam bitjaro gadoeang sudah tidak dipraktikkan lagi— kalaupun masih ada, hanya mungkin dipraktikkan oleh sebagian kecil masyarakat di pedalaman yang interaksi dengan orang luar kelompoknya masih sangat terbatas.
Sebagai wujud perencanaan bahasa, dengan melibatkan Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah mesti proaktif mengembalikan penulisan toponim sebagaimana bunyi yang hidup bersama masyarakat. Sebagian telah mengupayakannya, seperti Pemerintah Kota Pariaman yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nama Desa dan Kelurahan. Selain berfungsi sebagai perujuk yang membedakan satu tempat dan tempat lain (identification function), toponim juga berfungsi sebagai pengungkap wawasan masa lalu yang merefleksikan pengetahuan dan nilai-nilai budaya (cultural function). Semua itu mustahil terungkap selain oleh bahasa dan artikulasi lokal.
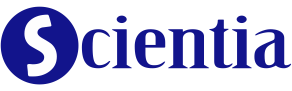









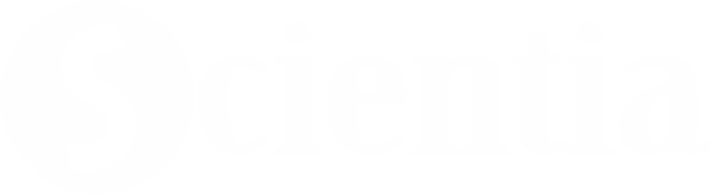
Discussion about this post