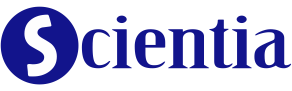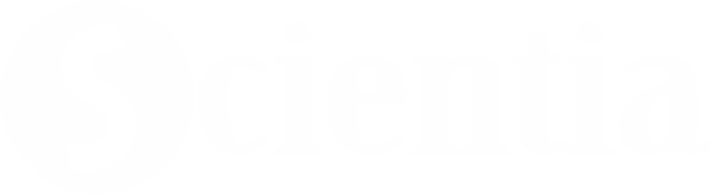Layakkah ini dijadikan kesimpulan? Perempuan Indonesia tidak mengenal mekap. Kata mekap saja sudah jelas-jelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu makeup. Dalam Kamus Merriam-Webster, kata ini bermakna cosmetics, yaitu ‘kosmetik (seperti lipstik, maskara, dan eyeshadow) yang digunakan untuk mewarnai dan mempercantik wajah). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekap adalah ‘tata rias muka’, sedangkan kosmetik adalah ‘1. berhubungan dengan kecantikan (tentang corak kulit); 2. obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir).
Jika mekap dan kosmetik merupakan bahan, cara, atau sesuatu yang digunakan untuk membuat seorang perempuan tampak cantik, berarti perempuan Indonesia masa lalu merupakan perempuan yang sudah cantik tanpa mekap, misalnya sebuah potret perempuan Indonesia di Instagram @potolawasofficial menggambarkan perempuan Indonesia dengan kesederhanaan dalam berkebaya tanpa mekap—yang bisa dibedakan dengan perempuan-perempuan Belanda yang ada di Indonesia pada saat itu.
Tokoh perempuan pejuang Indonesia, seperti Fatmawati, Rohana Kudus, Raden Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dien terekam dengan penampilan tanpa mekap yang menonjol. Bahkan, Titiah, perempuan Madura anggota Barisan Tjakra, peraih Medali Kruis van Verdienste dari Kerajaan Belanda pada 1949—medali yang diterima karena keberanian dan usaha membela kepentingan Kerajaan Belanda di medan perang—juga tampak tanpa polesan, rambutnya tanpa perawatan, serta tubuhnya juga tanpa kalung dan anting.
Dengan penghargaan yang diberikan Belanda, Titiah bisa saja tampil dengan wajah penuh polesan yang membuatnya tampak cantik di depan kamera. Apalagi, jika dibandingkan dengan perempuan-perempuan bangsawan pada masa itu yang sudah bekerja sama dengan Belanda, mereka sudah memiliki tata rias muka, lengkap dengan aksesori yang dikenalkan oleh perempuan Belanda. Artinya, perempuan Indonesia sejujurnya perempuan-perempuan yang awalnya tidak mengenal mekap sama sekali. Setidaknya inilah yang tercatat dalam kosakata bahasa Indonesia dalam KBBI.
Jika kita menelusuri kosakata bidang tata rias dalam KBBI Edisi VI di website kbbi.kemdikbud.go.id, kita akan menemukan 59 kosakata mengenai tata rias—yang tidak menggambarkan produk-produk kecantikan, seperti lipstik, bedak, maskara, perona pipi, dan perona mata. Kosakata yang ada di antaranya drogkap ‘alat pengering rambut berbentuk helm dan berpenyangga, berguna untuk mengeringkan rambut terutama saat sedang digulung atau dipakaikan jala’, tagelan ‘sanggul berbentuk bulatan yang terletak pada sebelah kanan penyawat sanggul pusung tagel’, dan lungsen ‘rambut palsu yang digunakan untuk mengikat dan menguatkan pemasangan sanggul tradisional’.
Selain itu, juga ada simpolong tatong (sanggul pengantin dari Bugis, Sulawesi Selatan), sanggul ukel tekuk (sanggul khas Yogyakarta), siput ekor kera (sanggul yang digunakan oleh perempuan di Bengkalis), gelung malang (sanggul yang digunakan oleh pengantin perempuan Palembang), sanggul ciwidey (sanggul pengantin dari daerah Jawa Barat), dan pusung gonjer (sanggul yang digunakan oleh perempuan Bali yang belum menikah). Seluruh kosakata ini menunjukkan bahwa rambut menjadi hal penting bagi perempuan Indonesia pada masa itu, baik yang menikah maupun yang belum menikah (pengaruh Islam dan fesyen muslim memang belum marak saat itu). Mekap, skincare, dan kosmetik belum menjadi kebutuhan mendasar.
Namun, masa berubah. Perkembangan teknologi dan budaya telah menyebabkan arah baru dalam dunia kecantikan, termasuk di Indonesia. Perempuan diminta untuk mempercantik diri dengan menggunakan serangkaian produk kecantikan. Bahkan, kini telah hadir banyak gerai yang mampu membuat perempuan Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik untuk mempercantik diri, seperti Nail Station yang mampu memberikan perawatan kuku, rambut, tata rias, estetika, bulu mata, dan spa.
Namun, satu hal yang membuat perempuan Indonesia terkejut adalah gelombang produk kecantikan yang datang bertubi-tubi dengan nama dan merek baru, dengan prosedur yang semakin lengkap dan rumit, serta dengan harga yang semakin gila dan menguras kantong. Gelombang produk kecantikan ini dibawa oleh bangsa asing dan sengaja menjajah bahasa Indonesia karena riasan tidak lagi sekadar bedak, lipstik, maskara, perona mata, dan perona pipi—kosakata yang sudah ada dalam KBBI, tetapi tidak menjadi bagian dalam bidang tata rias. Riasan terdiri atas perawatan kulit (skincare) dan makeup.
Perempuan Indonesia dipaksa untuk menjadikan standar kecantikan hari ini dengan wajah putih, glowing atau bercahaya (meskipun tidak akan bisa), dan merona dengan riasan wajah. Pemaksaan itu menuntut perempuan Indonesia untuk mengenal urutan skincare, seperti membersihkan wajah dengan sabun cuci muka (face wash), menggunakan toner, essence, serum, pelembap, dan sunscreen; serta mengenal urutan mekap, yang dimulai dengan primer, foundation, concealer, bedak, dan dilanjutkan dengan riasan mata (eyeshadow, eyeliner, maskara), lalu blush on, highlighter, dan terakhir lipstik dan setting spray.
Jika dilihat dari kosakata tersebut, tidak satu pun milik bangsa Indonesia. Semuanya merupakan produk yang dikenalkan oleh bangsa asing, baik Belanda, Inggris, maupun Korea—termasuk bedak, lipstik, dan sabun pencuci muka. Bahkan, face wash menjadi kosakata yang lebih bermakna ketika perempuan Indonesia menyebutkannya dalam berbelanja daripada sabun pencuci muka yang terkesan kampungan dan kolot.
Produk-produk ini yang kemudian menjadikan bangsa lain semakin kaya karena terus-menerus didesain, diiklankan oleh perempuan cantik, dan didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia. Hingga tanpa sadar, perempuan Indonesia akan berkata kepada perempuan Indonesia lainnya, “Perempuan itu harus cantik. Pakai skincare dong”, “Kamu kok pucat, gak pakai mekap?”; “Coba deh skincare ini, dijamin putih”; dan sejumlah kalimat yang menekan dan mendiskriminasikan perempuan-perempuan yang tidak mampu berdandan atau merias diri dengan produk-produk kecantikan terkini.
Beranjak dari asumsi tersebut, kemudian terbesit dalam pikiran saya, nama-nama yang berkenaan dengan produk-produk kecantikan ini sudah menjajah bahasa Indonesia sehingga tidak layak dimasukkan ke dalam bidang tata rias dalam KBBI. Sejumlah kata dibiarkan tanpa label tata rias, seperti bedak, maskara, lipstik, lipstik subam, pelembap bibir, perona mata, dan perona pipi. Padahal, produk ini merupakan produk yang dipakai dalam dunia kecantikan atau tata rias wanita.
Namun, asumsi ini kemudian terbantahkan jika kita melihat beberapa kata dalam bidang tata rias dalam KBBI. Ada kosakata serum eksfoliasi, krim kata, kuas alis, tongkat maskara, frimator, dan vaporiser, yang jelas-jelas dipakai sebagian untuk perawatan kulit dan sebagian untuk mekap. Adanya perbedaan ini tentu membawa kita pada kesimpulan bahwa Badan Bahasa tidak konsisten dalam memberi label pada kosakata bahasa Indonesia. Ada kosakata yang jelas-jelas merupakan kosakata bidang tata rias, tetapi tidak dilabeli dan dimasukkan ke dalam bidang tata rias.
Selain itu, kosakata bidang kecantikan yang menggambarkan tata rias perempuan Indonesia—akibat gelombang produk kecantikan—terus bertambah, misalnya ketika kita pergi ke toko kecantikan di mal, di sekian rak yang mereka tampilkan, akan terpajang produk-produk berupa beauty blender ‘alat mekap berbentuk spons yang digunakan untuk mengaplikasikan produk’; bronzer ‘produk mekap yang berwarna kecokelatan dan berfungsi memberikan kesan hangat dan dimensi pada wajah; browcara ‘produk kosmetik yang berbentuk maskara dan digunakan untuk merapikan dan menebalkan alis’; brow pomade ‘produk kosmetik yang bertekstur krim dan digunakan untuk membingkai dan mengisi alis’; clear pad ‘produk eksfoliasi wajah yang berbentuk seperti kapas’; clay mask ‘jenis masker wajah yang berbahan dasar tanah liat’; cleansing balm ‘produk pembersih wajah bertekstur seperti balsam’; cluster lashes ‘jenis bulu mata palsu yang terdiri beberapa helai bulu mata lalu digabung menjadi satu kumpulan’; dan concealer ‘krim atau bedak yang berguna untuk menyamarkan ketidaksempurnaan pada kulit’.
Bagi saya, membaca nama-nama itu saja sudah membuat lelah, apalagi menggunakan secara teratur untuk perawatan wajah dan mekap. Namun, perempuan Indonesia sudah menerima hal itu sehingga bersedia membeli dan memakainya di rumah; serta membayar jasa kecantikan—dengan menggunakan serangkaian produk tersebut—agar tampil cantik pada saat hari-hari istimewa.
Namun, kehadiran kosakata ini akan menjadi tanggung jawab berat bagi Badan Bahasa. Apa yang akan dilakukan dengan kehadiran kata ini? Apakah menyerapnya kosakata tersebut secara utuh, seperti kata serum ‘kosmetik ringan yang biasanya digunakan untuk wajah’? Apakah menyerap kosakata tersebut dengan melakukan perubahan bunyi, seperti lisptik dari lipstick, maskara dari mascara, mekap dari makeup, dan cosmetik dari cosmetics? Apakah menyerap dengan melakukan penerjemahan, seperti perona pipi dari blush on dan perona mata dari eye shadow?
Bentuk-bentuk serapan tersebut bisa diterima dalam bahasa Indonesia, tetapi yang kemudian menjadi permasalahan, apakah kata serapan tersebut akan bertahan dibandingkan kata aslinya, seperti skincare, beauty blender, bronzer, browcara, brow pomade, clear pad, clay mask, cluster lashes, dan concealer? Atau, kosakata tersebut akan memenangkan hati masyarakat Indonesia, khususnya para perempuan sehingga akan terus dipakai hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Sebuah fenomena yang sama dengan kata eyeliner yang sampai saat ini belum masuk ke dalam KBBI, padahal sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia.
Di KBBI kan ada garis mata? Jika ada yang menyangkal garis mata sebagai terjemahan dari eyeliner, kita pasti tidak sepakat karena maknanya dalam KBBI adalah ‘garis di atas mata sebagai batas kelopak mata agar mata terlihat lebih besar’. Makna ini tentu berbeda dengan makna yang dipahami perempuan Indonesia bahwa eyeliner adalah riasan yang digunakan untuk menonjolkan kontur mata.
Terkait kosakata yang dipakai masyarakat Indonesia mengenai tata rias dan kecantikan ini akhirnya menjadi PR (pekerjaan rumah) untuk peneliti bahasa dan khususnya Badan Bahasa hari ini. Perlu analisis mendalam tentang penyerapan kata ini ke dalam bahasa Indonesia. Akankah kita mendokumentasikan kosakata tersebut sebagai kosakata bahasa Indonesia atau (secara liar) membiarkan kosakata itu menjadi milik masyarakat tanpa terekam dengan baik?
Sebuah catatan bagi saya sebagai peneliti kosakata, yang fokus pada leksikografi atau kajian mengenai kamus, pertanyaan ini harus dijawab dengan menelusuri bukti-bukti kebahasaan mengenai kapan kata ini masuk ke dalam bahasa Indonesia, dalam konteks apa, bagaimana masyarakat dapat melafalkan ini tanpa jauh dari kosakata awal yang diserap, dan harus bertungkus lumus dengan proses penyerapan kata asing ke dalam bahasa Indonesia melalui sejumlah kaidah-kaidah kebahasaan.