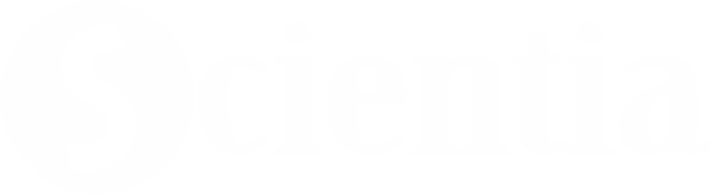Pada kesempatan ini, kita akan mengenal konsep semiotika sosial dalam ilmu bahasa (linguistik). Halliday (1978) menggambarkan hubungan bahasa dengan realitas sosial melalui konsep sistem semiotika sosial dalam tradisi linguistik fungsional sistemik (LFS). Bahasa sebagai semiotika sosial berarti bahwa bahasa sebagai sistem tanda linguistik merepresentasikan tanda-tanda dan symbol yang terdapat dalam kehidupan sosial.
Konsep bahasa sebagai semiotika sosial merujuk kepada tradisi semiotika yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Konsep semiotika disebut dengan semiotika sosial atau semiotika fungsional yang dijabarkan. Konsep semiotika sosial diperkenalkan oleh Halliday dalam buku Language as Social Semiotics dan Martin menyebut istilah semiotika sosial dengan human semiosis.
Semiotika sosial dalam pandangan LFS berarti bahasa dan tanda serta simbol yang menyertainya adalah sumber makna. Semiotika sosial berhubungan dengan sistem realisasi makna melalui pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan. Bahasa dan lingkungan semiotika sosial memiliki hierarkis. Masing-masing lapisan (layer) saling terkait satu sama lain. Hierarkis bahasa dan lingkungan semiotikanya terdiri atas grafologi/fonologi, gramatika, semantik, register, genre, dan ideologi (Halliday dan Hasan, 1978).
Halliday menyatakan bahwa pada tingkat struktur yang lebih abstrak, bahasa dibicarakan secara ekslusif (lebih atau kurangnya) karena teori fungsional bahasa, bahkan tata bahasa dapat dilihat sebagai struktur atau bentuk sosial. Artinya, bahasa tidak hanya dibicarakan pada sebatas struktur internal atau struktur teks, tetapi juga struktur eksternal yang disebut dengan konteks.
Pemikiran Halliday tentang konteks terinspirasi dari antropolog, Bronislaw Malinowski yang mencetuskan ide tentang konteks pada tahun 1923. Malinowski menyebut bahwa penafsiran makna ide atau gagasan dalam teks sebagaimana yang dimaksud oleh penutur bahasa harus mempertimbangkan lingkungan atau situasi yang menyertai bahasa tersebut (Wiratno, 2018). Lingkungan atau situasi yang menyertai disebut dengan konteks. Konteks merupakan bagian yang menentukan makna teks dan jenis/genre/variasi teks (Halliday dan Hasan, 1985;1989;1991;1992).
Halliday mengembangkan konsep Malinowski tentang konteks dengan membagi konteks atas dua, yaitu konteks situasi dan konteks sosial budaya. Konteks situasi merupakan konteks yang langsung menyertai teks dan dikelompokkan Halliday atas tiga, yaitu medan (field) berkaitan dengan topik, pelibat (tenor) merupakan partisipan yang terlibat dalam wacana, dan moda (sarana/media) yang merepresentasikan cara penciptaan teks. Kemudian, konteks sosial budaya dijelaskan Halliday sebagai konteks yang berkaitan dengan wawasan global dan institusional dari identitas penutur bahasa. Identitas tersebut direpresentasikan melalui agama, politik, bahasa, budaya, dan ideologi.
Identitas penutur bahasa dalam pendekatan sosiolinguistik tidak hanya berbentuk identitas tidak tetap atau tidak mutlak karena mengacu kepada atribut orang atau kelompok, tetapi juga mengacu kepada aspek yang dibangun secara dinamis dan muncul melalui perilaku sosial (social behavior). Wardhaugh dan Fuller (2015) menyatakan bahwa meskipun identitas individu yang terlihat atau yang menonjol, perhatian utama tetaplah kepada identitas sosial kelompok.
Persoalan kebahasaan dan hubungannya dengan semiotika sosial merupakan topik yang menarik dalam kajian wacana. Bahasa sebagai semiotika sosial dapat dilihat dalam berbagai wacana (teks), seperti wacana hukum/peraturan perundang-undangan, wacana sastra, wacana ekonomi, wacana kesehatan, dan wacana lainnya karena setiap wacana mengandung konteks situasi dan konteks sosual budaya. Di dalam konteks tersebut tanda-tanda atau simbol kebahasaan mengandung berbagai makna yang merepresentasikan identitas dan realitas sosial, misalnya simbol Burung Garuda dalam wacana hukum merepresentasikan legalitas dan kekuatan hukum yang dimiliki wacana tersebut, simbol Tuah Sakato dalam wacana Peraturan Daerah Sumatera Barat merepresentasikan ideologi masyarakat Minangkabau yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat sebagai simbol demokrasi, dan masih banyak lagi simbol semiotika sosial lainnya yang dapat direpresentasikan melalui bahasa.
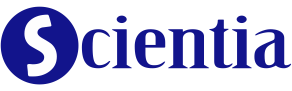





![CEO Moxa, Lim Lizal. [foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/03/Ceo-Moxa-e1742109932569-75x75.png)