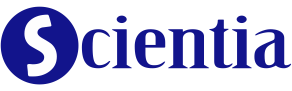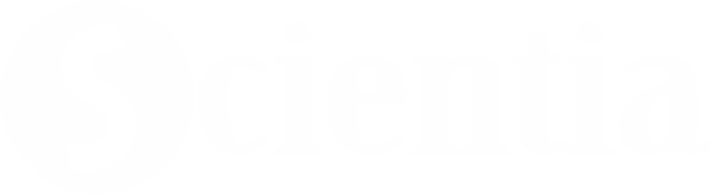Oleh: M. Subarkah
Oleh: M. Subarkah
(Alumni Sastra Indonesia dan Mahasiswa Prodi S2 Linguistik FIB Universitas Andalas)
Bahasa mencerminkan zaman dan merekam jejak kehidupan manusia dari percakapan sehari-hari hingga karya besar yang melintasi generasi. Bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, melainkan medan pertempuran identitas, arena kreativitas, sekaligus panggung sandiwara. Pada generasi hari ini, bahasa tampil dengan wajah penuh warna. Bahasa bisa serius dalam sastra, cair dalam slang, dan dramatis dalam keseharian. Bahasa anak muda bak mozaik, campur aduk, tidak selalu rapi, tetapi justru indah karena sarat kejutan.
Cobalah duduk di sebuah kafe tempat anak muda berkumpul. Dengarkan percakapan di meja sebelah. Ada yang berkata, “Aduh, gabut banget nih, gaskeun healing yuk, biar nggak overthinking.” Kalimat itu jelas tidak akan ditemukan di buku teks sekolah. Kata gabut merujuk pada bosan tak ada kerjaan, gaskeun berarti ayo lanjut, healing dimaknai liburan, dan overthinking diartikan kebanyakan pikiran. Semuanya campur aduk: Indonesia, Inggris, bahkan sedikit rasa humor. Akan tetapi, anak muda yang mendengarnya langsung paham. Mereka tidak kebingungan. Itulah kekuatan slang: menciptakan kedekatan, sekaligus menjadi kode rahasia yang menandai siapa yang “insider” dan siapa “outsider.”
Bahasa gaul selalu bergerak cepat. Generasi 1990-an mengenal bokap-nyokap, ngetop, gaul abis. Awal 2000-an ramai dengan alay, lebay, geje. Kini istilah itu bergeser ke bestie, flexing, mager, insecure, vibes. Esok, bisa jadi akan lahir istilah baru dari TikTok, meme, atau bahkan salah ketik yang kemudian viral. Slang itu seperti mode fashion: datang dan pergi, tetapi selalu kembali dengan wajah baru. Jika bahasa resmi adalah jas rapi untuk rapat kenegaraan, slang adalah kaus oblong dengan gambar band indie, santai, cair, tetapi penuh identitas.
Namun, anak muda tidak hanya hidup dari bahasa gaul. Mereka juga masih berhubungan dengan sastra, meskipun dalam bentuk yang berbeda dari generasi sebelumnya. Sastra kini hadir bukan hanya di perpustakaan atau lembaran buku tipis yang berdebu. Ia tampil di Instagram dalam bentuk puisi singkat yang dipadukan dengan ilustrasi. Ia muncul di Wattpad dalam cerita cinta remaja yang ditulis dengan campuran bahasa puitis dan slang. Ia bahkan muncul di TikTok dalam bentuk video membaca puisi dengan latar musik sendu.
Menariknya, anak muda tidak segan mengawinkan sastra dengan bahasa gaul. Sebuah puisi yang viral misalnya berbunyi, “Aku mencintaimu bukan ala drama Korea, tapi kayak wifi gratis nyambung tanpa perlu ditanya password-nya.” Sekilas terasa konyol, tapi di situlah kreativitasnya. Sastra yang dulu terkesan berat kini jadi lebih ramah, dekat, bahkan lucu. Anak muda sedang membuktikan bahwa bahasa puitis bisa hidup berdampingan dengan bahasa sehari-hari, tanpa harus terjebak dalam aturan kaku.
Fenomena bahasa anak muda juga memperlihatkan sisi performatif yang kuat. Kata-kata mereka tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memainkan peran. Saat seorang mahasiswa menulis status “aku anak rantau, tetap gas terus kuliah walau dompet tipis”, ia tidak sekadar bercerita. Ia sedang menciptakan citra mandiri, tangguh, sekaligus humoris. Saat seorang remaja menulis “fix aku gagal”, itu bukan sekadar laporan, melainkan dramatisasi untuk mencari empati, tawa, atau sekadar perhatian. Bahasa anak muda adalah pertunjukan. Setiap kata adalah dialog dalam teater kehidupan sehari-hari.
Kekhawatiran terhadap bahasa gaul tentu tidak baru. Dulu kata gue dan elo dianggap kasar. Kini keduanya sudah biasa dipakai dalam sinetron, film, bahkan iklan. Bahasa yang awalnya dianggap “merusak” justru akhirnya menjadi arus utama. Bisa jadi, sepuluh tahun mendatang kata gaskeun atau flexing sudah masuk ke kamus resmi. Bahasa selalu berubah, dan perubahan itu adalah tanda kehidupan. Bahasa yang kaku, justru tanda bahasa yang mati.
Jika kita tarik ke belakang, fenomena ini tidak jauh berbeda dengan sejarah bahasa itu sendiri. Bahasa Melayu pernah menyerap kata-kata Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, hingga Inggris. Dari raja, agama, syukur, sampai kantor dan internet, semuanya adalah pinjaman dari luar. Bahasa Indonesia tumbuh justru karena kelenturannya menerima perubahan. Anak muda hari ini, dengan segala slang dan sandiwara bahasanya hanya sedang melanjutkan tradisi itu.
Bahasa adalah cermin masyarakat. Dari cara anak muda berbicara, kita bisa membaca karakter generasi ini kreatif, cepat berubah, penuh humor, kadang dramatis, tetapi selalu punya cara baru untuk mengekspresikan diri. Sastra memberi kedalaman, slang memberi vitalitas, dan sandiwara bahasa memberi ruang bermain. Tiga wajah ini membuat bahasa anak muda tidak bisa dipandang remeh. Ia adalah medan kreativitas yang sedang menulis sejarahnya sendiri.
Mungkin bagi sebagian orang, bahasa anak muda terdengar aneh, bahkan memusingkan, tetapi bukankah setiap generasi selalu punya bahasanya sendiri? Orang tua dulu punya istilah jablai atau cupu yang sekarang sudah jarang terdengar. Sama saja. Bedanya, generasi hari ini punya media sosial yang membuat bahasa mereka terdokumentasi, menyebar luas, dan seringkali abadi. Apa yang hari ini hanya sekadar lelucon bisa jadi esok masuk dalam penelitian linguistik atau karya sastra.
Pada akhirnya, sastra, slang, dan sandiwara bahasa anak muda adalah bagian dari denyut kehidupan bahasa Indonesia itu sendiri. Ia bukan pertentangan, melainkan perpaduan. Ketiganya menegaskan bahwa bahasa tidak pernah selesai, selalu berpentas, dan selalu mencari bentuk baru. Di tangan anak muda, bahasa bukan hanya alat bicara, melainkan juga karya seni, hiburan, dan pernyataan diri.