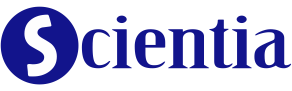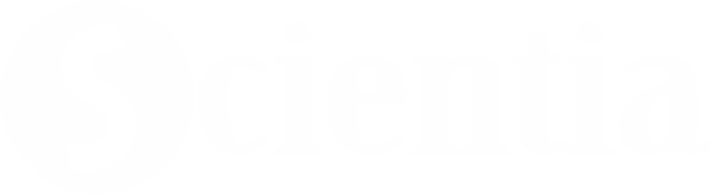Oleh: Ahmad Hamidi
(Dosen Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas)
Apa pentingnya makna? Sejauh mana ia menggambarkan realitas penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari? Dalam berkomunikasi, sebagai manusia pada umumnya, pemaknaan kita lebih sering berdasarkan intuisi. Kita merasa seolah-olah dapat memahami makna bahasa tanpa perlu mengikuti perkuliahan semantik di bangku-bangku perguruan tinggi. Namun, sekali lagi, apa pentingnya makna? Siapa yang berkuasa dalam menentukan makna bahasa? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi titik tolak yang menggugah kesadaran kita tentang posisi penting makna dalam kehidupan. Makna tersebut yang dibahas dalam buku Makna Kata yang ditulis oleh Ria Febrina, Dosen Program Studi Sastra Indonesia Universitas Andalas. Buku berjumlah 208 halaman itu merupakan kumpulan esai bahasa yang diterbitkan oleh Kabarita pada Juni Tahun 2025.
Apabila pembacaan kita atas buku karya Dr. Ria Febrina, S.S., M.Hum., akademikus bidang linguistik dari Universitas Andalas, ini hanya sampai tataran tekstual, kita mungkin akan tiba pada simpulan dangkal bahwa makna ditentukan oleh negara melalui perangkatnya, yakni Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang memegang kendali atas Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sebagai rujukan bahasa yang merepresentasikan negara, KBBI memang berperan besar dalam menentukan kata dan makna yang digunakan oleh publik. Kamus hadir sebagai otoritas makna: ia merekam, memvalidasi, sekaligus menjadi penentu mana kata yang “benar” dan mana yang “belum diakui”.
Sialnya, Makna Kata tidak berhenti sampai di situ.
Apabila pembacaan kita terhadap buku setebal 208 halaman ini melampaui teksnya, kita akan menemukan tiga poin penting yang hendak disampaikan penulisnya. Pertama, bahasa adalah milik penuturnya. Kedua, bahasa—khususnya kata dan makna dalam konteks buku ini—terus berubah. Ketiga, makna dalam bahasa tidak pernah tunggal dan final.
Bentuk dan makna bahasa bukanlah produk dominasi negara atau menitik dari langit begitu saja. Bahasa dan maknanya, sebagaimana adagium orang Minangkabau, mambasuik dari bumi, bukan manitiak dari ateh. Dengan kata lain, keduanya datang dari bawah, dari pemiliknya, masyarakat penggunanya. Penyusun kamus, dengan demikian, hanya berwenang mencatat, bukan mengatur atau mengendalikan cara masyarakat menggunakannya. Kamus hadir sebagai dokumentasi atas kata dan makna yang hidup, bukan sebagai alat penghakiman terhadap apa yang sah dan tidak sah di hadapan negara.
Apabila suatu kata dan maknanya belum tercatat dalam kamus, itu tidak berarti bahwa kata dan makna tersebut salah atau tidak sah. Ketiadaan di dalam kamus bukanlah penyangkalan terhadap eksistensinya di masyarakat. Kamus, dengan seluruh kerangka normatifnya, tetap merupakan produk buatan manusia yang terikat oleh batasan-batasan metodologis dan institusional.
Penyusun KBBI merumuskan sejumlah syarat agar suatu kata dan maknanya dapat dimasukkan ke dalam daftar lema, yakni keunikan, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia (fonotaktis), eufoni atau keindahan bunyi, konotasi positif, dan frekuensi penggunaan yang tinggi. Namun, syarat eufoni dan konotasi positif patut dipersoalkan. Sebab, dengan menetapkan keduanya sebagai syarat, KBBI telah melakukan seleksi nilai atas bentuk bahasa, mana yang baik dan mana yang buruk bagi warga negara. Padahal, dalam praktik sosial, dinamika bahasa melampaui beban moral apa pun karena ia tidak senantiasa hadir dalam bentuk yang elok seperti seorang bocah manis yang menjilat-jilat es krim di siang bolong. Ia mencerminkan realitas sosial masyarakat. Sepanjang digunakan dengan frekuensi tinggi oleh masyarakat, dengan kandungan makna yang unik, suatu kata berhak dipungut ke dalam KBBI.
Dalam kajian bahasa, terdapat dua pendekatan, yakni preskriptif dan deskriptif. Preskriptif berarti memandang fenomena berbahasa menggunakan kacamata kuda: benar atau salah. Sementara itu, deskriptif berarti memandang bahasa secara lebih moderat sebagai sebuah fenomena faktual, tanpa kecenderungan menghakimi. Keduanya hanya perlu ditempatkan sesuai porsinya masing-masing. Pendekatan preskriptif mungkin tepat diterapkan dalam konteks formal dan administratif, seperti dokumen hukum atau kebijakan negara. Namun, dalam konteks kolokial atau kebudayaan populer, pendekatan deskriptif membukakan ruang yang lebih luas bagi keragaman bahasa. Maksud saya, kita tidak perlu repot-repot mengkritik penggunaan bahasa di siniar YouTube, tetapi—kalau bernyali—kita perlu mengkritik institusi apabila keliru menerapkan ejaan dalam penulisan, umpamanya, gelar rektor yang luar biasa panjangnya.
Sebagai penulis, Ria Febrina tampak telah memosisikan diri secara proporsional di antara kedua pendekatan tersebut. Di satu sisi, ia merujuk pada kamus-kamus sebagai dasar argumentasinya. Di lain sisi, ia juga tidak segan mengkritisi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara isi kamus dan realitas kebahasaan, yang tampak pada, misalnya, esai berjudul “Perempuan”. Sikap kritis yang tidak destruktif itu menjadikan buku terbitan Kabarita ini sebagai contoh yang baik dalam memperlakukan kamus. Sebab, meminjam ungkapan Holy Adib, seorang jurnalis dan esais bahasa, “kamus bukanlah kitab suci”. Ia dibuat oleh manusia sehingga isinya bisa saja keliru. Lagi pula, kerja kamus berhenti pada satu titik sesaat setelah ia telah dilepas kepada publik, sedangkan pada saat yang sama dinamika kata dan maknanya terus melaju bersama penggunanya.
Salah satu kekuatan buku ini terletak pada upaya penulisnya menghasilkan karya yang bersifat diakronis. Sumber tertua yang digunakannya bertarikh 1942, yakni Kamoes Indonesia susunan E. St. Harahap. Penulisnya tidak hanya memperkarakan kata dan maknanya pada satu waktu tertentu, tetapi juga menelusuri jejak perubahan makna kata dalam lintasan sejarah, yang mungkin berubah, berkembang, atau bahkan menyimpang dari bentuk awalnya. Perubahan-perubahan semacam itu adalah keniscayaan. “There is no such thing as a living language that fails to change”, kata Robert Lawrence Trask, profesor bahasa University of Sussex, dalam bukunya Why Do Language Change? (2010).
Di sisi lain, penulisnya piawai dalam bertutur. Selain menyajikan data-data semantis yang bersumber dari berbagai kamus, ia menyampaikan data-data tersebut dalam teks yang enak dibaca sehingga mudah dipahami. Bahasa yang digunakannya lentur. Kata-kata yang dipilihnya dekat dengan pengalaman berbahasa kita sehari-hari. Muatan yang berat dalam teks tersebut mudah dinikmati karena penulisnya menyajikan secara ringan. Lebih daripada itu, penulisnya tidak sekadar menyajikan substansi tentang keberbagaian makna, tetapi juga membabarkan kepada kita kisah penyebaran suatu kata “baru” lalu menjadi kata dengan makna yang konvensional digunakan oleh masyarakat lintas etnis, seperti tampak pada esai berjudul “Teka-Teki Silang”, “Klangenan”, dan “Micin”. Ia mengajak kita bertamasya kuliner Korea, lalu menyelami pandangan dunia Jawa tentang gacoan, dulur, klangenan, dan lain sebagainya.
Penulisan buku yang merupakan pumpunan esai ini tentu menuntut ketekunan tinggi dalam membolak-balik kamus lintas usia; membandingkan makna dari satu kamus ke kamus lainnya; serta mencurahkan perhatian detail, konsistensi metode, dan ketajaman analisis. Penulisnya berhasil melakukan itu dengan baik. Sebagai sebuah karya intelektual, saya merekomendasikan buku ini menjadi bacaan penunjang bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Semantik dan Leksikologi—juga bagi siapa pun yang tertarik memahami cara bahasa dan maknanya bekerja sebagai atribut sosial yang berdinamika. Makna Kata mengajak kita merenungkan kembali cara makna dibentuk, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam praktik sosial. Makna Kata memang memperpanjang daftar buku bermutu seputar bahasa dan kebahasaan. Namun, sebagaimana kata pepatah, “tak ada gading yang tak retak”. Terdapat sekurang-kurangnya dua hal yang menjadi catatan atas buku ini.
Pertama, entah hanya pada eksemplar yang saya baca, terdapat cacat produksi pada halaman 45–46. Halaman yang tidak tercetak secara sempurna menyulitkan pembacaan. Kedua, kesalahan tik dan penggunaan kata nonbaku—yang mungkin saja disengaja oleh penulisnya untuk mengejar efek bunyi tertentu, semacam gaya selingkung.
Bentuk-bentuk yang luput dari koreksi akhir, di antaranya, Bahasa Bahasa (sampul belakang, baris 30; seharusnya Badan Bahasa) kosataka (halaman 35, brs. 17; seharusnya kosakata), masyaratat (hlm. 35, brs. 26; seharusnya masyarakat), yang (hlm. 36, brs. 4; seharusnya tidak ada), prasati (hlm. 36, brs. 18; seharusnya prasasti), Leipzing (hlm. 37, brs. 4; seharusnya Leipzig), diadaan (hlm. 67, brs. 12; seharusnya diadakan), mandu2 (hlm. 76, brs. 13; seharusnya mandu), drama korea (hlm. 74, brs. 1; seharusnya drama Korea), Indonea (hlm. 77, brs. 29; seharusnya Indonesia), sres (hlm. 91, brs. 27; seharusnya stres), diasosiakan (hlm. 93, brs. 3; seharusnya diasosiasikan), diumpakan (hlm. 93, brs. 8; seharusnya diumpamakan), memilki (hlm. 176, brs. 6; seharusnya memiliki), galic (hlm. 176, brs. 14; seharusnya garlic). Sementara itu, penggunaan kata nonbaku, di antaranya, mempublikasikan (hlm. vii, brs. 27; baku memublikasikan), mempopulerkan (hlm. 24, brs. 5; baku memopulerkan), mengkonfirmasi (hlm. 29, brs. 26; baku mengonfirmasi), sepakbola (hlm. 30, brs. 32; baku sepak bola), gangsing (hlm. 72, brs. 22; baku gasing), handal (hlm. 80, brs. 18; baku andal), bernafas (hlm. 91, brs. 25; seharusnya bernapas), terlanjur (hlm. 91, brs. 30; seharusnya telanjur), mempercayai (hlm. 174, brs. 4; baku memercayai), tercermin (hlm. 176, brs. 34; baku tecermin).
Catatan-catatan tersebut tidak akan cukup mampu mengganggu kredibilitas karya. Catatan-catatan tersebut justru dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan cetakan berikutnya sekaligus menunjukkan bahwa perhatian terhadap detail adalah bagian dari penghargaan terhadap kerja intelektual.
Bahasa adalah organisme yang bergerak bersama kita. Ia tidak statis, tidak tunggal, dan tidak dimiliki satu otoritas. Makna adalah hasil dari dialog terus-menerus antara bahasa dan penggunanya. Makna Kata mengajarkan kita untuk memandang bahasa secara lebih adil, lebih terbuka, dan lebih manusiawi. Kembali ke pertanyaan yang menjadi tajuk tulisan ini: Apa pentingnya makna? Pertanyaan tersebut, dengan sendirinya, akan terjawab ketika kita tuntas membaca Makna Kata.