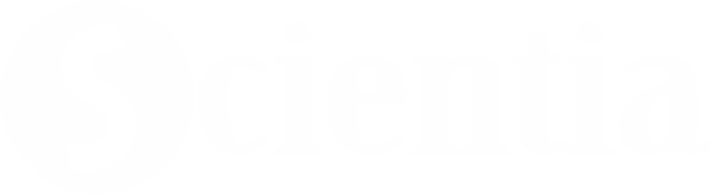Oleh: Sindi Rahmawati Putri
(Mahasiswa Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas)
Novel tetrologi Pulau Buru merupakan salah satu karya monumental dari sastrawan Indonesia Pramoedya Ananta Toer yang ditulis ketika ia mendekam di penjara dan sempat dilarang peredarannya selama beberapa masa karena dianggap mengandung pesan Marxisme-Lenimisme yang tersirat pada kisah-kisahnya. Novel ini menampilkan latar abad ke-20 di Hindia-Belanda atau yang sekarang kita kenal dengan Indonesia dan mengungkapkan sejarah keterbukaan nasionalisme pada awal kebangkitan nasional. Tidak hanya menceritakan sejarah, novel ini juga mengandung permasalahan-permasalahan sosial dan politik pada zaman itu sehingga menjadi media kritik bagi penulisnya.
Latar sosial yang menjadi lahirnya novel-novel ini adalah perjuangan-perjuangan pribumi untuk menyamakan kelas sosial yang sama karena banyaknya ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh pribumi yang dicerminkan dalam novel ini dan juga sebagai produk kolonial yang tertulis dalam catatan sejarah bangsa Indonesia.
Tokoh utama novel ini adalah seorang pemuda Jawa bernama Minke yang berusaha untuk melampui batas-batas sosial dan budaya pada zaman itu. Meskipun dirinya adalah golongan pribumi, Minke mendapatkan pendidikan yang cukup baik. Ia bersekolah di sekolah Belanda yaitu HBS (Hogere Burger School) dan mendapatkan pendidikan Eropa. Hal itu membuat Minke kehilangan jati dirinya sebagai seorang pribumi. Namun, banyak hal yang perlahan membuatnya kembali menemukan jati dirinya terutama semenjak ia kehilangan istri tercintanya, Annelis.
Sebagai seorang pribumi, tokoh Minke mengalami banyak marginalisasi dan hak-haknya diabaikan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Marginalisasi merupakan salah satu bentuk intimidasi terhadap suatu kelompok, dalam hal ini Minke sebagai pribumi. Meskipun Minke mendapatkan pendidikan di sekolah Eropa tapi ia tidak pernah dianggap setara dengan orang Eropa ataupun Belanda, sehingga membuatnya sulit diterima di lingkungan sosial dan budaya orang-orang Eropa. Kolonial Belanda pada saat itu menganggap bahwa bangsa Eropa adalah bangsa yang memiki kekuasaan dan merupakan penguasa. Oleh karena itu, mereka merasa pribumi jauh berada di bawah mereka bangsa Eropa.
Meskipun dengan kecerdasan yang dimilikinya, Minke tetap dipandang rendah oleh teman-teman sekolahnya. Selain bangsa yang memiliki kekuasaan, bangsa Eropa juga dianggap tidak patut untuk disamakan dengan bangsa kulit berwarna (orang-orang Asia). Hal ini menjadi salah satu bentuk diskriminasi ras yang dialami oleh Minke sebagai seorang pribumi. Tidak hanya itu, terdapat juga kosakata ejekan yang ditujukan kepada Minke yang mempunyai arti yang tidak mengenakkan, seperti monyet, harem, dan philogynik.
Kata-kata memiliki arti yang buruk, monyet berarti ‘kera yang bulunya berwarna abu-abu dan mempunyai ekor panjang’, harem berarti ‘bagian rumah yang terpisah untuk kaum wanita, kelompok wanita yang dikawini oleh satu pria’, dan philogynik yang berarti ‘laki-laki yang senang terhadap perempuan’.
Pernikahan antara Minke dan Annelis pun sempat menjadi pertentangan di antara keluarga dan masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya yang dijunjung pada saat itu. Minke yang seorang pribumi dianggap tidak pantas untuk bersanding dengan Annelis yang merupakan keturunan Belanda. Hubungan kelas sosial dan ras dianggap tabu. Sistem hukum yang berlaku pada saat itu juga tidak mendukung pernikahan antar-ras dan kelas sosial karena adanya ketidaksetaraan di mata hukum yang akan membuat pernikahan tersebut tidak bisa diakui seperti pernikahan-pernikahan pada umumnya. Oleh karena hal tersebut, maka Minke dan Annelis menjadi dikucilkan dan semakin diperumit karena Minke juga bergerak di bidang politik sehingga pernikahan mereka dianggap sebagai ancaman yang dapat menggangu stabilitas sosial dan politik yang di bangun kala itu.
Sementara itu, di bidang hukum juga terjadi ketidaksetaraan yang di dapat karena Minke hanyalah seorang pribumi. Minke sulit mendapat keadilan karena peradilan dikuasai oleh pihak Belanda. Dalam hal ini ras dan kasta menjadi pembeda sistem hukum. Novel-novel tersebut memberikan gambaran jelas mengenai betapa kejamnya hukum Belanda yang diberlakukan terhadap pribumi. Akses-akses terhadap hukum disulitkan sehingga sering terjadi pelanggaran hak-hak dan penyalahgunaan kekuasaan. Hukum bisa saja dimanipulasi oleh pihak Belanda untuk kepentingan mereka. Hal ini terjadi ketika Pengadilan Putih dengan tidak bijaksana seakan keluarga Nyai Ontosoroh yang sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pengadilan saat itu akan selalu mempersalahkan pribumi jika terjadi perselisihan antara warga Eropa dengan pribumi dengan cara licik yang dibuat-buat.
Di samping itu, tokoh-tokoh pribumi lain pada novel ini juga mengalami diskriminasi yang lebih menyengsarakan seperti tanam paksa yang membuat mereka harus menyerahkan hasil pertaniannya kepada para penjajah, perampasan harta benda, dan juga perampasan terhadap anak istri mereka. Hal-hal inilah yang kemudian membuka mata Minke untuk melakukan perubahan sebagai seorang pribumi sehingga muncul semangat nasionalisme dalam diri Minke sebagai seorang pribumi. Meskipun pada novel pertama yaitu ‘Bumi Manusia’ tokoh Minke ini digambarkan sebagai seorang yang sangat menyukai tentang Belanda, ia sampai bersekolah di sekolah Belanda dan mempelajari hal-hal berbau Belanda.
Selain kondisi sosial dan politik, serta ketidaksetaraan, ada hal-hal penting lainnya yang menarik pada tetralogi Pulau Buru ini. Ada perubahan dan pertentangan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam menghadapi kolonialisme, seperti antara tradisi dan modernitas, kekuasaan dan keadilan yang menjadi ciri khas pada saat itu. Ada juga resistensi norma sosial yang ditunjukkan dengan adanya konflik dalam pernikahan Minke dan Annelis. Dengan adanya berbagai permasalahan-permasalahan tersebut akhirnya membawa Minke kepada perjalanan menemukan identitas diri sebagai seorang pribumi dan pencarian makna kemanusiaan yang adil dan juga setara. Ada banyak pertentangan dan konflik yang tentunya dihadapi oleh tokoh Minke dalam proses pencarian identitas diri ini.
Beberapa hal dilakukan Minke dalam melawan diskriminiasi dan marginalisasi yang dihadapi terdapat pada narasi yang mencerminkan semangat melawan ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi. Minke memanfaatkan pendidikannya untuk meningkatkan kesadaran dirinya. Ia menjadikan itu semua sebagai kekuatan untuk bisa menyadari ketidaksetaraan yang terjadi. Pertentangan terhadap penikahannya dengan Annelis pun dilakukan perlawanan terhadap aturan dan norma yang ketika itu menghambat kebebasan dan kesetaraannya. Pernikahan tersebut juga sebagai deklarasi perlawanan terhadap batasan-batasan sosial dan rasial. Tidak hanya perlawan fisik, Minke juga melibatkan perlawanan batin terhadap keadilaan dan kemanusiaan.
Perjuangannya untuk bisa mendapat keadilan juga menciptakan penentangan terhadap sistem hukum yang selalu memihak kolonial. Dengan perlawanan tersebut, semangat akan berkobar-kobar sebagai bentuk tekad untuk melawan penjajahan dan mencapai sebuah kemerdekaan. Nyatanya Tindakan tersebut tidak hanya memberi dampak bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberi insprirasi kepada masyarakat sekitar. Hal itu memicu perubahan persepsi dan sikap masyarakat terhadap sistem kolonial. Tokoh Minke ditempatkan sebagai seorang pahlawan yang berjuang dalam memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan bagi masyarakat pribumi pada masa Hindia-Belanda.
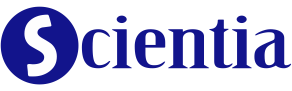







![Kantor PDAM Kota Padang.[foto : net]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/07/FB_IMG_17535045128082-350x250.jpg)