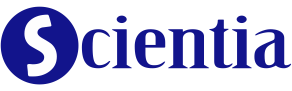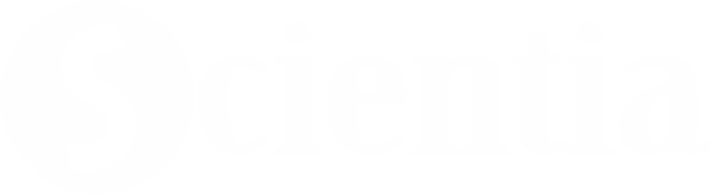Oleh: M. Subarkah
(Mahasiswa Prodi S2 Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas)
Di tengah gemerlap dunia digital dan derasnya arus informasi, generasi muda hari ini hidup dalam pusaran yang paradoksal. Mereka lebih terkoneksi dari sebelumnya namun juga lebih kesepian. Mereka memiliki akses luas terhadap pengetahuan dan kesempatan, tetapi kerap kehilangan arah dan makna. Di antara fenomena-fenomena psikologis yang merebak, “overthinking” menjadi salah satu kata kunci yang sering diucapkan, ditulis, bahkan dijadikan identitas oleh generasi Z. Namun di balik candaan dan meme tentang overthinking, tersimpan persoalan yang lebih dalam: krisis makna hidup di tengah budaya serba cepat dan penuh tekanan.
Overthinking sering dipahami sebagai kebiasaan berpikir berlebihan terhadap sesuatu baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan hingga menimbulkan kecemasan yang tidak produktif. Dalam konteks Gen Z, fenomena ini semakin kuat karena mereka tumbuh dalam budaya digital yang menuntut kecepatan dan kesempurnaan. Media sosial membentuk ruang di mana perbandingan menjadi hal biasa: pencapaian orang lain, penampilan ideal, hingga kesuksesan palsu yang sering dipoles filter. Akibatnya, banyak anak muda merasa tertinggal, tidak cukup, dan terus-menerus menilai diri sendiri.
Kondisi ini diperparah oleh tekanan sosial dan ekonomi. Banyak di antara mereka yang hidup dalam ketidakpastian: biaya hidup meningkat, lapangan pekerjaan tidak stabil, dan standar keberhasilan semakin kabur. Dalam situasi seperti itu, pikiran berputar tanpa arah menjadi pelarian sekaligus jerat. Mereka berpikir terlalu banyak, tapi merasa tidak bergerak ke mana pun. Dunia yang terlalu bising membuat hati mereka semakin sunyi.
Fenomena ini bisa diamati dari aktivitas sehari-hari anak muda. Misalnya, seseorang menunda mengambil keputusan karena takut salah, lalu menghabiskan waktu berjam-jam untuk memikirkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Ada juga yang terus membandingkan hidupnya dengan teman-teman di media sosial, merasa selalu kurang, hingga merasa kehilangan kendali atas kebahagiaannya sendiri. Inilah wajah overthinking modern: aktivitas mental yang tampak produktif, tapi sejatinya melelahkan dan membingungkan.
Jika ditelusuri lebih dalam, overthinking bukan hanya masalah mental atau psikologis, tetapi juga masalah makna. Viktor E. Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi Nazi, menulis bahwa penderitaan terbesar manusia bukan karena kesakitan fisik, tetapi karena kehilangan tujuan hidup. Dalam bukunya Man’s Search for Meaning, ia menegaskan bahwa manusia yang kehilangan makna akan mudah tersesat dalam kekosongan batin, dan salah satu bentuknya adalah kecemasan tanpa arah sebuah ciri khas yang kini banyak dialami Gen Z.
Budaya modern menuntun manusia pada pencarian kebahagiaan instan: validasi, likes, views, dan pengakuan publik. Namun semakin keras seseorang mengejar itu semua, semakin hampa ia rasakan di dalam. Overthinking menjadi gejala dari ketidakpuasan eksistensial seseorang terus memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan, siapa dirinya, dan apakah hidupnya berarti. Semua pertanyaan itu muncul tanpa jawaban karena fondasi nilai yang dulu memberi arah kini mulai pudar.
Bagi sebagian orang, agama dan spiritualitas seharusnya menjadi tempat kembali untuk menemukan keseimbangan. Namun, di kalangan Gen Z, spiritualitas sering tereduksi menjadi tren. Banyak yang mengutip kata-kata bijak dari media sosial tanpa benar-benar merenungkan maknanya. Akibatnya, krisis makna tetap berlanjut, hanya dibungkus dalam estetika “healing” dan “self-love” yang sering kali dangkal.
Salah satu akar dari budaya overthinking adalah tekanan untuk selalu produktif dan tampil sempurna. Dalam masyarakat yang memuja kesuksesan dan efisiensi, manusia dinilai dari seberapa cepat ia bekerja, seberapa banyak ia mencapai target, dan seberapa baik ia terlihat di hadapan publik. Istirahat dianggap malas, gagal dianggap aib. Maka tidak heran jika banyak anak muda merasa cemas ketika tidak melakukan apa-apa padahal diam dan tenang justru bagian penting dari proses hidup.
Budaya ini menciptakan lingkaran setan: seseorang bekerja keras untuk mencapai ekspektasi, lalu merasa tidak cukup, kemudian tenggelam dalam pikiran sendiri. Di sinilah overthinking tumbuh subur bukan karena mereka tidak berdaya, tetapi karena mereka terperangkap dalam standar sosial yang tidak manusiawi. Mereka terus menganalisis masa depan yang belum terjadi, menyesali masa lalu yang tak bisa diubah, dan lupa menikmati kehadiran saat ini.
Overthinking tidak hanya memengaruhi kesehatan mental individu, tetapi juga hubungan sosial. Anak muda yang terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri sering kesulitan membangun komunikasi yang sehat. Mereka cenderung menarik diri, curiga berlebihan, atau sulit mempercayai orang lain. Dalam konteks keluarga, teman, atau komunitas, hal ini menciptakan jarak emosional yang tak terlihat. Bahkan interaksi sederhana, seperti ngobrol santai di kafe atau diskusi daring, bisa berubah menjadi sumber stres karena mereka selalu menimbang setiap kata dan konsekuensinya.
Fenomena ini juga terlihat di sekolah dan kampus. Banyak mahasiswa Gen Z yang menunda mengerjakan tugas karena takut hasilnya tidak sempurna, atau menghindari diskusi kelompok karena khawatir pendapatnya dianggap salah. Akibatnya, mereka kehilangan pengalaman sosial yang esensial dan kesempatan untuk belajar dari kesalahan, padahal kedua hal itu sangat penting untuk pertumbuhan pribadi dan profesional.
Untuk keluar dari jerat overthinking, langkah pertama adalah menumbuhkan kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu sempurna. Manusia tidak diciptakan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk memahami dan menghidupi maknanya sendiri. Kesadaran ini bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan berdamai dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaan diri.
Menemukan makna tidak selalu berarti menemukan jawaban besar. Kadang, makna hadir dalam hal-hal kecil: membantu orang lain, menulis, berdoa, mendengarkan musik, atau sekadar berbicara jujur tentang perasaan sendiri. Dalam kesederhanaan itulah seseorang mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu “pasti,” yang penting adalah tetap berjalan dan bertumbuh.
Selain itu, penting bagi Gen Z untuk merekonstruksi hubungan mereka dengan teknologi. Media sosial seharusnya menjadi alat, bukan tuan. Dengan mengatur waktu penggunaan, menghindari perbandingan berlebihan, dan mencari komunitas yang suportif, seseorang dapat menjaga kesehatan mental dan emosinya. Di sisi lain, pendidikan dan lingkungan sosial juga perlu memberi ruang bagi anak muda untuk gagal tanpa takut dihakimi, agar mereka bisa belajar dan berkembang secara alami.
Budaya overthinking adalah cermin dari zaman yang kehilangan arah. Zaman di mana manusia tahu banyak hal, tapi lupa untuk benar-benar memahami. Gen Z, dengan segala tantangan dan kelebihannya, sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengubah arah peradaban menuju keseimbangan baru antara pikiran, perasaan, dan makna hidup.
Di kota, kampus, atau kamar pribadi, setiap kali seorang anak muda berhenti sejenak dari arus informasi dan menatap dirinya sendiri, ia sedang memulai perjalanan baru. Perjalanan untuk berdamai dengan ketidakpastian, menghargai proses, dan menemukan makna di tengah kebisingan. Overthinking bukanlah musuh, tetapi alarm yang menandai bahwa kita perlu berhenti, bernapas, dan menata kembali prioritas hidup. Hidup tidak selalu harus sempurna, tetapi hidup yang sadar, penuh makna, dan selaras dengan diri sendiri adalah bentuk kematangan tertinggi. Dan bagi Gen Z, kesadaran itu menjadi kunci untuk membangun kehidupan yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih manusiawi di tengah dunia yang serba cepat ini.